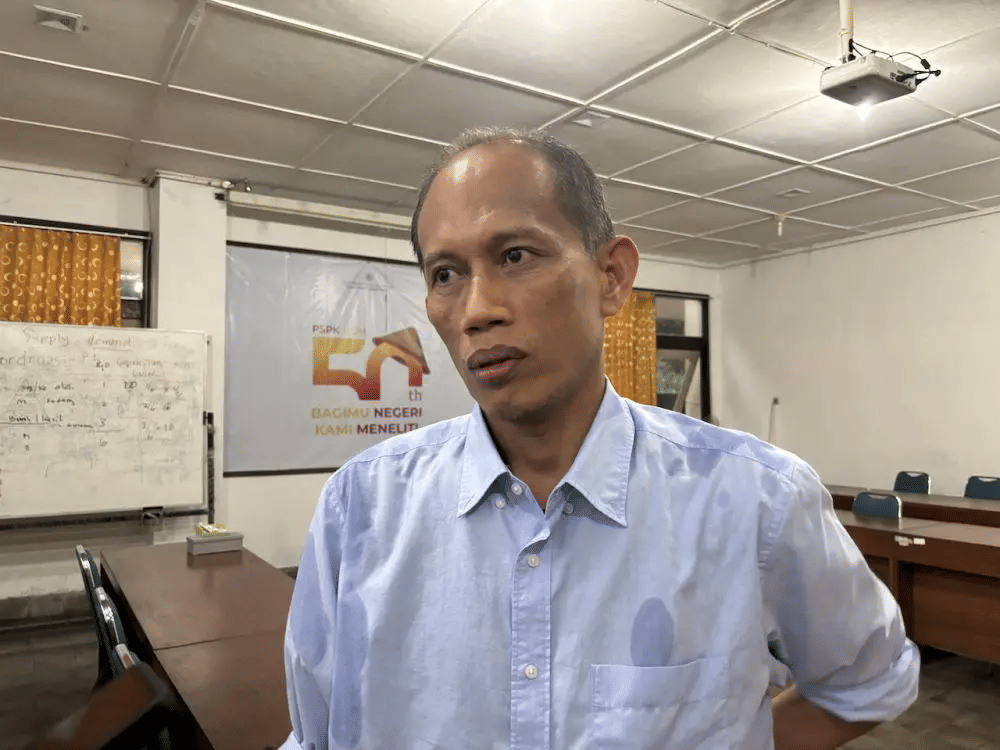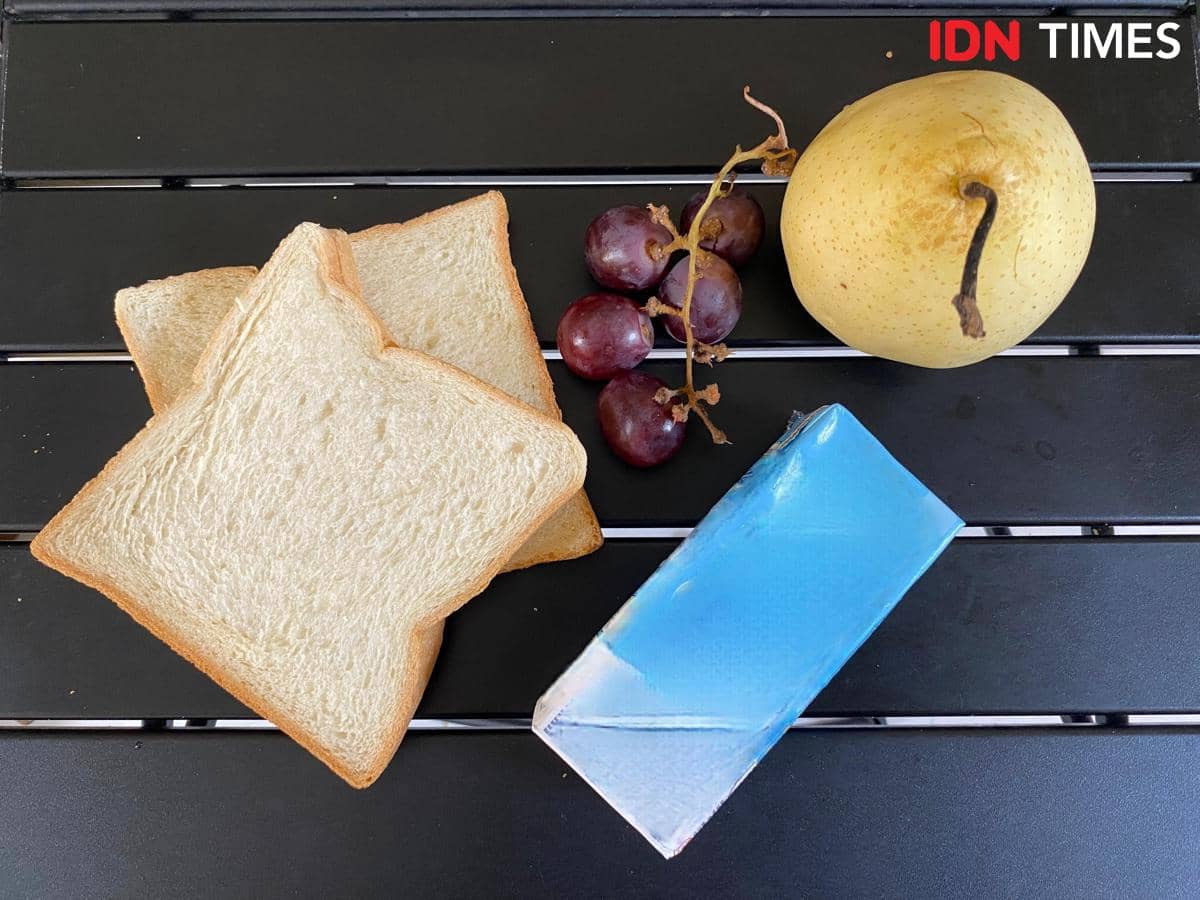Diskusi Diskoma UGM Bahas Viralitas sebagai Narasi Budaya di Ruang Digital

Viralitas muncul seiring pergeseran ideologi komunikasi di era medsos
Dipengaruhi algoritma dan logika viralitas berbeda di setiap platform
Perlu kesadaran kritis dan literasi digital untuk mengendalikan narasi media sosial
Yogyakarta, IDN Times - Diskusi Komunikasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Diskoma UGM) menggelar diskusi publik Kaleidoskop 2025 bertajuk “Viralitas Narasi Media Sosial dan Makna Budaya yang Dipercaya” pada Kamis, 29 Januari 2026. Acara ini berlangsung secara daring dan terbuka untuk umum sebagai respons atas dinamika komunikasi digital yang kian kompleks.
Diskusi tersebut menghadirkan dua dosen Ilmu Komunikasi UGM, Dian Arymami dan Mufti Nurlatifah sebagai pembicara, didampingi mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM, Daffa Lazuardy Noer Sy, sebagai moderator. Melalui forum ini, Diskoma UGM mengajak peserta melihat viralitas media sosial bukan sekadar fenomena sesaat, tetapi juga sebagai narasi budaya yang membentuk makna, kepercayaan, dan cara berpikir masyarakat masa kini.
1. Viralitas muncul seiring pergeseran ideologi komunikasi di era medsos

Dian Arymami menyebut viralitas muncul seiring pergeseran ideologi komunikasi di era media sosial. Menurutnya, penyebaran pesan kini banyak ditentukan oleh mood dan style, bukan lagi semata argumen rasional. Daya tarik emosional justru menjadi kunci, bahkan emosi telah berubah menjadi bentuk pengetahuan dalam budaya afektif masyarakat digital.
“Emosi tidak lagi bisa diposisikan hanya sebagai reaksi personal, tetapi sudah menjadi cara masyarakat memproduksi dan mempercayai makna, apalagi dalam konteks viralitas di media digital,” jelas Dr. Dian dalam keterangan yang diterima IDN TImes, Senin (2/2/2026).
Ia menambahkan, media sosial dirancang untuk mengelola perhatian dan emosi publik. Akibatnya, ruang diskusi yang tercipta sering berbeda dari konsep ruang publik rasional dalam teori klasik. Ruang viral, kata dia, lebih banyak bekerja lewat simbol, citra, dan representasi yang membentuk persepsi kolektif. Viralitas pun tidak selalu mendorong perubahan tindakan, tetapi dapat memengaruhi kepercayaan dan orientasi berpikir masyarakat.
“Yang viral sering kali tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi bekerja di ruang simbolik yang memengaruhi cara orang memandang realitas yang ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Dian menilai wacana digital bisa menjadi hegemonik ketika bertemu fragmentasi hasrat dan relasi kuasa. Makna di media sosial tidak pernah tunggal atau stabil, melainkan terus diproduksi serta diperebutkan berbagai kepentingan. Ia menyebut kondisi ini mencerminkan late modernism yang ditandai percepatan informasi, fragmentasi pengalaman, dan perasaan keterasingan yang kian kuat.
“Makna selalu bergantung pada hasrat yang muncul dan relasi kuasa yang menyertainya, sehingga viralitas menjadi arena kontestasi makna,” tegas dosen FISIPOL UGM tersebut.
2. Dipengaruhi algoritma

Mufti Nurlatifah menekankan perlunya membedakan viralitas dan popularitas dalam membaca lanskap media sosial saat ini. Menurutnya, viralitas merujuk pada penyebaran konten digital secara luas dalam waktu singkat, dengan pola naik turun yang cepat dan didorong praktik berbagi oleh pengguna. Sementara popularitas, kata dia, dibangun lewat strategi komunikasi yang terencana dan berlangsung jangka panjang, seperti yang kerap dilakukan merek atau figur publik.
“Viral itu tidak dirancang untuk bertahan lama, ia bekerja secara cepat dan fluktuatif,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap platform memiliki logika viralitas berbeda, sejalan dengan mekanisme algoritma yang digunakan. Dr. Mufti memaparkan sejumlah jenis konten yang berpotensi viral, mulai dari social currency, triggers, emotion, public visibility, practical value, hingga stories.
“Konten viral tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkelindan dengan konteks sosial, emosi, dan kebiasaan pengguna,” sambung Dr. Mufti.
Dalam perkembangan terbaru, ia menambahkan media sosial pada periode 2025–2026 bergerak menuju fase yang semakin algoritmik. Jika sebelumnya arus informasi banyak ditentukan relasi pertemanan, kini perilaku pengguna menjadi dasar utama rekomendasi konten. Fenomena ini dikenal sebagai TikTokification, yang memicu meningkatnya personalisasi sekaligus mengurangi kontrol individu atas paparan informasi.
“Sekarang bukan lagi siapa teman kita, tetapi apa yang kita tonton, kita sukai, dan kita hentikan yang dibaca oleh algoritma,” jelasnya.
3. Perlu kesadaran kritis dan literasi digital

Dr. Mufti menilai ekosistem media sosial saat ini tidak bisa dilihat semata sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk, karena pengguna turut terlibat aktif dalam produksi dan penyebaran konten. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa kesadaran kritis dan literasi digital yang kuat, pengguna rentan terjebak dalam hegemoni narasi yang dibentuk oleh desain sistem media itu sendiri.
“Media sosial bukan sepenuhnya buruk, tetapi ketika kita tidak memiliki kesadaran kritis, kita mudah digiring oleh narasi yang sudah dirancang oleh sistemnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi digital penting agar pengguna tidak hanya menjadi konsumen pasif. Menurutnya, masyarakat perlu memahami sekaligus mengendalikan relasi kuasa yang bekerja di balik algoritma dan arsitektur media sosial.
“Kesadaran inilah yang memungkinkan kita keluar dari logika hegemonik dan membaca media sosial secara lebih reflektif,” pungkasnya.
Diskusi Kaleidoskop 2025 yang digelar Diskoma UGM menyimpulkan bahwa viralitas perlu dipahami sebagai formasi budaya yang kompleks dan tidak berjalan linier. Di tengah percepatan informasi serta ketidakstabilan makna, peserta diajak lebih reflektif dalam menyikapi arus viral di media sosial.
“Kita hidup di zaman yang tidak selalu runtut, dan dalam kondisi seperti ini, tersesat justru menjadi bagian dari pengalaman komunikasi itu sendiri,” pungkas kedua pemateri dalam sesi closing statement.