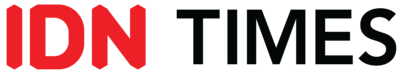Kwee Thiam Tjing, Jurnalis Tionghoa Indonesia yang Terlupakan
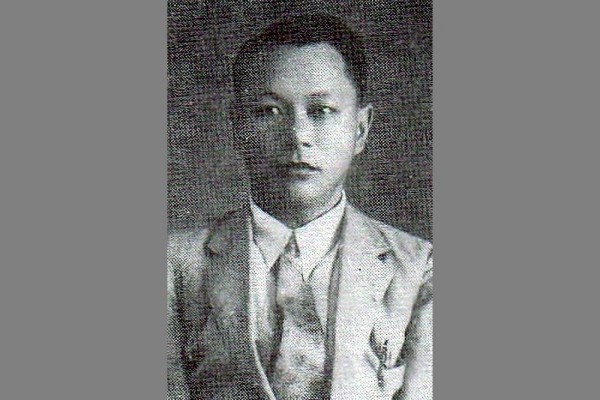 Foto diri Kwee Thiam Tjing. (Wikimedia)
Foto diri Kwee Thiam Tjing. (Wikimedia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times – Tak banyak yang tahu siapa Kwee Thiam Tjing. Namanya seolah mendadak muncul ketika Indonesianis berkewarganegaraan Amerika, almarhum Ben Anderson menyunting kembali buku Kwee terbitan 1947 yang berjudul “Indonesia Dalem Api dan Bara” pada 2004. Sejak itu, orang mulai membicarakannya, juga menulis tentangnya. Sebelumnya, sosoknya seolah hilang di bawah tumpukan buku.
Kwee adalah sosok jurnalis Tionghoa yang meramaikan khazanah media-media publik sejak 1920. Ia lahir di Pasuruan pada 9 Februari 1900 dan wafat pada 28 Mei 1974 di Jakarta. Jika masih hidup, Kwee akan meniup lilinnya pada 9 Februari mendatang untuk merayakan ulang tahun ke-120.
Kwee lebih banyak menulis kolom di surat kabar Sin Tit Po, media massa terbitan orang-orang Tionghoa di Surabaya. Selebihnya, ia menjadi koresponden untuk Soeara Publiek, Pewarta Soerabaia, dan redaktur Pemberita Djember. Bahkan pada usia 74 tahun, Kwee masih aktif menulis di Indonesia Raya.
“Terakhir sebagai orang tua yang (menulis) cerita tentang pengalamannya,” kata peneliti sejarah dan penulis Arief W Djati dalam diskusi bertema Ngobrolin Tjamboek Berdoeri di Bentara Budaya Yogyakarta, Rabu (28/1) lalu.
Baca Juga: Nama Samaran Kwee, dari Tjamboek Berdoeri hingga Tangan Majit
1. Lihai berbahasa Belanda, Hokkian, Melayu, dan Jawa
Ayahnya bekerja di pabrik gula. Kwee adalah anak laki-laki pertama dalam keluarganya. Kelahirannya itu membuat Kwee menjadi anak yang diistimewakan ketimbang anak laki-laki kedua. Pada usia 4-16 tahun, Kwee diindekoskan di rumah keluarga Belanda totok yang bekerja sebagai kapitan di Pasuruan.
Istilah ‘diindekoskan’ masa itu, menurut Arief, tidaklah sama dengan tinggal di kos atau asrama. Melainkan diangkat anak.
“Karena Kwee nakal,” kata Arief.
Lantaran itu pula, Kwee bisa ditambah gelar “sia”. Serupa dengan anak pesantren yang dipanggil dengan sebutan “gus”.
Ayahnya meninggal sebelum Jepang masuk. Ibunya pun tinggal bersama Kwee sebagai anak lelaki tertua. Sepeninggal ibunya pada 1947 usai kemerdekaan, Kwee dan adiknya pun pindah ke Jakarta pada 1949.
Perpindahan dari satu daerah ke daerah lain sedari kecil, mau tak mau, Kwee beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Tak terkecuali dalam hal berbahasa. Dia pun fasih menggunakan beragam bahasa untuk menyesuaikan di lokasi di mana dia tinggal.
Di dalam keluarga, Kwee biasa menggunakan bahasa Hokkian. Kemudian berbahasa Belanda di dalam keluarga Belanda dan di sekolah. Lingkungan kampungnya di Jawa Timur membuat dia bisa berbahasa Jawa, bahkan Madura. Dan ketika berpindah ke Jakarta, Kwee terbiasa berbahasa Melayu. Kelak kemahirannya berbahasa gado-gado itu tercermin dalam tulisan-tulisannya.
2. Sedari kecil suka berkelahi
Ketika indekos di dalam keluarga Belanda, Kwee disekolahkan di ELS (Europeesch Lagere School) di Malang. Meski bersekolah di lingkungan orang-orang Eropa, Kwee punya nyali berkelahi. Kenapa? Zaman itu juga sudah ada perundungan.
“Kwee dibilang Cina loleng buntute digoreng. Dia berusaha melawan,” kata Arief.
Tak ayal, tiap pulang sekolah selalu berkelahi. Perkelahian dilakukan di dalam lingkungan sekolah.
“Kalau di luar sekolah pasti dihukum, ditahan (pemerintah kolonial),” kata Arief.
Dalam perkelahian pun, lanjut Arief, anak Belanda totok dinilai lebih gentle.
“Kalau kalah, ya bilang kalah. Minta ampun, tak dipukul lagi,” kata Arief.
Sebaliknya, yang satu ras dengannya atau pun Belanda Indo, meski minta ampun tetap terus dipukul.
“Terus dipukul beberapa kali. Pura-pura gak dengar (kalau minta ampun),” kata Arief.
3. Sempat tinggal di Malaysia
Selama menjadi jurnalis, Kwee sempat menulis buku berjudul Indonesia Dalem Api dan Bara pada 1947. Kemudian hijrah ke Malaysia ikut menantu dan anaknya. Menantunya bekerja di pabrik obat, juga seorang pelatih bulutangkis.
“Kesan saya, karena dia sudah gak ada kerjaan lagi,” kata Arief menafsirkan alasan kepindahan Kwee ke Negeri Jiran.
Di rumah, Kwee menghabiskan waktu mendengarkan gambang kromo, keroncong, juga gending-gending Jawa. Kemudian 1971, dia kembali ke Indonesia bersama anak dan menantunya. Sisa waktunya dihabiskan dengan menulis obituari selama 1971-1973 di harian Indonesia Raya yang dikelola Mochtar Lubis. Setidaknya ada 34 judul dari 91 penerbitan selama itu.
Lima bulan setelah koran itu diberedel pasca peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), Kwee wafat. Jenazahnya sempat dimakamkan di pemakaman Tanah Abang I, Jakarta. Usai lahan pekuburan digusur untuk dibangun Taman Prasasti, sisa tulangnya dikremasi dan abunya ditebar di Laut Jawa. Tak ada media massa masa itu yang menuliskan tentang kepergiannya.
Baca Juga: Klowor, Sang Pelukis Kucing Hitam Putih hingga Warna-Warni