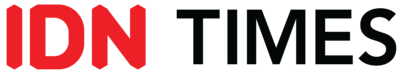Predator Seksual di Kos-Kosan (2): Janji Kampus Tak Selalu Manis
 Ilustrasi Anti-Kekerasan Seksual (IDN Times/Galih Persiana)
Ilustrasi Anti-Kekerasan Seksual (IDN Times/Galih Persiana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Menjelang akhir 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Aturan tersebut untuk merespons kasus-kasus kekerasan seksual di kampus yang kerap terabaikan.
Hanya saja untuk kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa di luar kampus, seperti di kos, lokasi kuliah kerja nyata (KKN), kampus acap kali cuci tangan dengan alasan terjadi di luar kampus.
“Kalau kampus gak bertanggung jawab kan malah bubrah,” kata Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Defirentia One Muharomah dalam wawancara daring, 12 Januari 2022.
Dan kondisi itu menjadi tantangan yang dihadapi dalam proses advokasi sebelum Permendikbudristek itu lahir. Dan ketika lahir, aturan menteri itu dinilai One tak cukup.
“Harus ada aturan di kampus. Ada inisatif kampus untuk membuat kewenangan dan kewajiban yang lebih detail,” paparnya.
Tim Kolaborasi Liputan Kekerasan Seksual di Indekos yang terdiri dari IDN Times Jogja, Jaring.id, Koran Tempo, Konde.co, dan Suara.com menyusun tulisan: Bagaimana kampus-kampus menyikapinya?
Baca Juga: Predator Seksual di Kos-Kosan (1): Siapa pun Bisa Jadi Pelaku
1. Advokasi korban kekerasan seksual yang berawal dari kepedulian
Sebut saja Laksmi, salah satu dosen perguruan tinggi di Yogyakarta yang merasa berjuang sendiri. Kepeduliannya untuk membantu para korban kekerasan seksual, baik terjadi di kampus maupun luar kampus, tak selalu berjalan mulus. Suatu ketika, upaya mengadvokasi penyintas berbuah sanksi terhadap pejabat yang menjadi pelaku.
“Karena pelaku berisiko terhadap banyak hal, maka saya berani,” kata Laksmi kepada tim kolaborasi, 13 Januari 2022.
Namun, seringnya pihak kampus menyimpulkan kekerasan seksual terjadi karena faktor suka sama suka.
“Meskipun sudah diperjuangkan, endingnya yang menang pelaku,” kata Laksmi.
Bahkan ketika pelaku adalah mahasiswa dan diupayakan membuatnya tak mudah untuk lulus agar mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, upaya itu tak didukung pihak kampus. Terduga pelaku justru mendapat dukungan kampus sehingga cepat lulus.
Kondisi tersebut, menurut Laksmi tak terlepas dari budaya patriarki di kampus. Seperti nama baik kampus. Tak heran, ketika mahasiswa mulai menunjukkan atensi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di kampus, mendiskusikannya, dan memperjuangkannya, Laksmi sangat mendukung.
“Saya ini nobody. Hanya dosen yang peduli. Karena one is too much. Satu (korban) pun harus dicegah,” tegas Laksmi.
Dan perjuangan Laksmi banyak mendapat tantangan. Berbagai ancaman pernah didapatkan dan Laksmi berusaha melupakan.
“Saya dianggap orang yang gak mau kompromi. Karena itu, saya gak disukai. Itu risiko saya,” kata Laksmi.
2. Kampus-kampus ‘berjanji’ mengakomodir, asalkan ada bukti
Sejauh ini, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Sumaryanto mengaku belum ada aturan soal penanganan kasus kekerasan seksual di kampusnya. Namun tengah diproses, termasuk pembentukan satuan tugas. Mengingat kampus negeri merupakan bagian dari kementerian.
“Apalagi UNY punya jargon leading and director education. Itu bagian dari komitmen membangun karakter yang mulia,” kata Sumaryanto, 22 Januari 2022.
Aturan itu nanti juga akan mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa, tenaga pendidik, baik yang terjadi di dalam maupun luar kampus, seperti lokasi KKN, ruang praktik, juga kos.
“Iya. Tetap kami jangkau dengan ketentuan itu,” kata Sumaryanto.
Sementara Universitas Islam Indonesia (UII) pun telah mempunyai aturan serupa yang terangkum dalam Peraturan UII tentang Pencegahan dan Penanganan Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual yang ditetapkan pada 24 November 2020. Dan Rektor UII Prof. Fathul Wahid menyatakan aturan itu juga menjangkau kasus yang terjadi di luar kampus.
“Ada, di sana masuk semua. Asal dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan kan tidak tahu. Dan ada buktinya. Nanti kami buat tim dan proses semua,” papar Fathul.
Baca Juga: Tim Investigasi Temukan Bukti Perkosaan, UMY Pecat Mahasiswa MKA
3. Zero tolerance dalam penanganan kekerasan seksual di kampus
Sekretaris Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Gugup Kismono, menyebutkan pihaknya telah mempunyai Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat UGM, berikut standar operasi prosedurnya.
Namun sejumlah penyesuaian tengah dilakukan, salah satunya berproses di fakultas. Seperti mendorong para penyintas dan pihak lain untuk melapor ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Khusus Penanganan Kekerasan Seksual UGM untuk proses yang lebih baik dan tepat. Semisal merekrut psikolog dari lulusan UGM untuk melakukan psychological first aid.
“Prinsipnya zero tolerance kami gunakan untuk menjalankan aturan dan program penanganan kekerasan seksual,” kata Gugup dalam pesan WhatsApp kepada tim kolaborasi, 12 Januari 2022.
Meski diakui Gugup, salah satu kendala dalam proses penanganan kasus adalah ketiadaan saksi atau bukti lain yang kuat. Seperti rekaman video atau CCTV.
“Tim etik harus mencari bukti-bukti lain yang kuat untuk menyusun rekomendasinya,” kata Gugup.
Sebut saja, seperti merunut peristiwa-peristiwa terkait sebelumnya, membaca gesture saat sidang, mempelajari track record penyintas maupun terlapor, dan sebagainya.
“Prinsipnya, demi kebaikan. Jadi fleksibilitas peraturan untuk perlindungan kepada yang lemah akan diutamakan,” kata Gugup.
4. Patriarki, privilege, dan permisif jadi akar masalah kekerasan seksual
Rifka Annisa, menurut One, punya pengalaman 14 tahun dalam upaya melibatkan laki-laki dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis gender sejak 2007. Dari situlah, lembaga itu juga mempelajari akar masalah dari sisi pelaku apa.
“Kami menemukan, kenapa laki melakukan kekerasan seksual,” kata One.
Pertama, konsep budaya patriarki masih bermanifest dalam perilaku sehari-hari laki-laki. Ketimpangan relasi kuasa dalam budaya itu yang memposisikan laki-laki lebih berkuasa ketimbang perempuan, laki-laki mengontrol perempuan dengan cara kekerasan.
“Laki-laki menggunakan ketimpangan itu untuk melakukan bujuk rayu. Perempuan tak berdaya,” kata One.
Kedua, privilege. Ada budaya yang seolah memberi keistimewaan kepada laki-laki. Seperti riset terhadap laki-laki muda yang melakukan kekerasan di Papua, Jakarta, dan Purwokerto.
“Mereka tidak merasa bersalah, karena bagi mereka melakukan itu hak dan wajar,” kata One.
Ketiga, budaya permisif. Dalam konstruksi sosial, seolah ada justifikasi yang dilakukan pelaku bukanlah kekerasan. Bahkan ada yang membela pelaku dan membuat alibi yang membenarkan alibi pelaku. Budaya permisif membuat pelaku terlindungi dalam lingkungannya.
Budaya permisif juga acap terlihat dalam kebijakan yang dibuat kampus.
“Kalau kampus membuat aturan yang tidak sensitif korban, pasti akan merugikan korban. Ini bentuk budaya permisif,” kata One.
Baca Juga: Kekerasan Seksual pada Anak Tak Selalu Tinggalkan Luka, Tapi Trauma