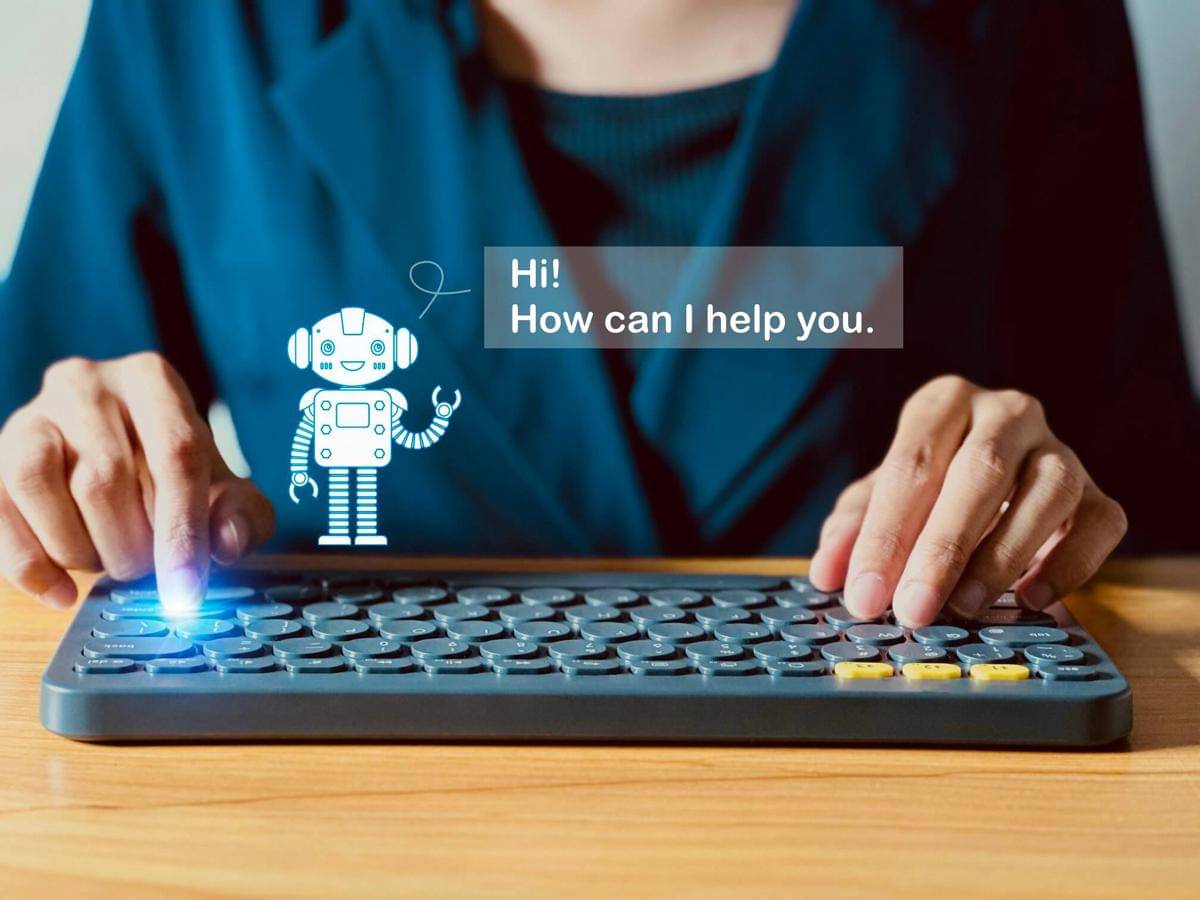Cerita Perempuan Korban Penggusuran YIA, Bersiasat demi Bertahan Hidup

Kulon Progo, IDN Times – Tuginah, 50 tahun, dan puluhan warga lain adalah rombongan terakhir yang bertahan di dalam pagar kawasan yang akan disulap menjadi Yogyakarta International Airport (YIA) di pesisir Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Mereka bersikukuh menolak meninggalkan rumah dan lahan garapan demi bandara. Tak terhitung berapa kali perempuan yang menjanda usai suaminya meninggal pada 2016 itu berdiri berhadapan dengan aparat keamanan.
Tuginah masih ingat ketika bersama kakak perempuannya menghadang ratusan polisi yang mengamankan proses pengukuran lahan dan rumahnya. Ia juga menjerit ketika mesin ekskavator melantakkan tanaman cabainya yang akan dipanen pada 2018 pagi itu. Menyisakan onggokan cabai merah ranum yang berubah jadi sampah digulung tanah. Tak berapa lama, giliran rumah tempat berlindung dia dan empat anaknya gentian dilibas backhoe. Semua dihadapi penuh nyali.
“Sebagai perempuan, aku gak mau di belakang. Harus di depan. Meski kalah,” kata Tuginah saat ditemui di rumah barunya di Dusun Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, 26 April 2020.
Kawasan yang disebut di dalam pagar itu sudah jadi bandara megah. Rencana pemindahan semua maskapai penerbangan dari Bandara Adisutjipto ke YIA pada akhir Maret 2020 lalu gagal karena virus corona. Namun promosi kemewahan bandara itu gencar diletupkan. Seolah ada yang terlupakan, ketika pesawat terbang dan mendarat di sana, ada air mata ratusan perempuan yang tumpah di atasnya.
“Penggusuran sudah diberitakan. Tak ada perubahan. Persoalannya, tidak ada keberlanjutan isu,” kata aktivis pendamping warga terdampak bandara, Pitra Hutomo dalam workshop “Pemberitaan Berbasis Gender pada Perempuan Terdampak Pembangunan Infrastruktur” di Auditorium Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 15 Januari 2020.
Tuginah adalah potret perempuan korban penggusuran bandara. Tak banyak yang tahu perempuan adalah kelompok rentan yang terdampak berat. Lahan pertanian subur mereka dirampas. Pekerjaan sebagai petani dan penghasilan hilang. Janji dapat pekerjaan di bandara diganjal diskriminasi umur, pendidikan, kompetensi, dan jenis kelamin. Perempuan harus bersiasat untuk menyambung hidup.
“Pembangunan itu sangat maskulin. Lingkungan sangat feminin. Di mana-mana lingkungan berkelindan dengan persoalan-persoalan perempuan,” kata jurnalis senior, Bambang Muryanto.
1. Uang jadi sumber konflik antarwarga

Hingga titik akhir penggusuran Juli 2018, tercatat ada 66 kepala keluarga (KK) yang menghuni 37 rumah yang bergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) masih bertahan. Mereka tetap menyatakan menolak meninggalkan rumah yang akan digusur menjadi bandara. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan masih dipegang.
Usai lahan dan rumah tak bersisa, warga hidup di tenda-tenda. Perpecahan tampak. Sebagian warga ingin mengambil uang ganti rugi dari PT Angkasa Pura (AP) I Yogyakarta yang dititipkan di Pengadilan Negeri Wates. Lantaran terdesak ekonomi dan butuh tempat bernaung.
Musyawarah digelar. Putusan mengambil atau tidak ganti rugi diserahkan masing-masing warga. Sebagian mengambil uang. Sofyan, 36 tahun masih bertahan menolak. Seandainya bandara sudah berdiri dan ditawari kembali ke sana pun, Sofyan mau.
“Tanah di sana masih milik kami. Kan uang ganti rugi belum kami ambil,” kata Sofyan kukuh saat ditemui di kediamannya, 23 Februari 2020.
Sampai kini pun, Sofyan tak mau tahu lahan dan rumahnya digunakan untuk apa di bandara. Sekadar lewat terowongan bandara sepanjang 1,4 km yang diresmikan Presiden Joko Widodo pun, Sofyan menolak.
“Ingat dulu warga digitukan (digusur), gak bisa hilang. Gak ada rasa ingin tahu, ingin lihat,” kata Sofyan.
Tercatat, pro kontra telah terjadi ketika proses sosialisasi rencana pembangunan bandara berlangsung. Rombongan awal yang menyatakan sepakat menerima ganti rugi itu sudah tinggal di relokasi. Di Palihan, Jaten, Glagah, dan sebagian Jangkaran.
“Uang itu bikin perpecahan,” kata Sofyan.
Namun komunikasi dan silaturahmi masih terjalin antara penolak dan penerima. Masih ada undangan kenduri dari warga pro dan kontra. Meski diakui Sofyan, rasa canggung pun ada.
“Kalau ketemu, bahas hal lain. Jangan sampai terputus,” kata Sofyan yang berharap Syawalan usai lebaran nanti bisa bertemu lagi.
Tuginah, rombongan akhir yang terpaksa menerima ganti rugi, menyempatkan berkomunikasi. Biasanya ketika bertemu di sekolah untuk antar jemput anak-anak mereka. Saling curhat, saling cerita.
“Ada yang panen terong, cabai, dibawa. Siapa yang mau,” kata Tuginah.
Dukuh Kragon II Wiharto, 54 tahun, yang tinggal di relokasi Palihan membenarkan. Dampak sosial yang meruncing akibat perbedaan sikap pro kontra mulai melunak. Jika ada warga hajatan, saling undang, datang, dan saling bantu.
“Dulu yang pro dan kontra seperti minyak dan air,” kata Wiharto.
Tak hanya antar warga. Perpecahan pun terjadi dalam satu keluarga. Lahan warisan jadi sengketa karena pewarisnya ada yang menerima dan menolak.
“Antara bapak dan anak bisa crah. Alhamdulillah, sekarang membaik,” kata Wiharto.
Data PN Wates tertulis, dana konsinyasi dari AP yang dititipkan Rp854 miliar. Hingga 16 April 2020, sudah ada 222 berkas permohonan pengambilan ganti rugi yang diproses. Menurut juru bicara PN Wates Edy Sameaputty, pengambilan uang ganti rugi tak berbatas waktu. Jika belum diambil saat ini, uang masih dititipkan di sana.
“Kalau ada sengketa atau pemiliknya belum diketahui, silakan mengajukan permohonan sidang penetapan penitipan ganti rugi,” kata Edy.
2. Jadi petani itu yang penting punya lahan

Tuginah sekeluarga sempat menumpang berteduh di rumah warga di luar pagar (kawasan di luar terdampak bandara) delapan bulan usai rumah dan lahannya rata tanah. Makan sehari-hari mengandalkan dapur umum yang dikelola sejumlah relawan yang melakukan pendampingan dan advokasi terhadap warga penolak bandara. Relawan juga menggalang donasi untuk uang saku anak-anak mereka.
Dan Tuginah mengangkat kedua tangan. Bersama 25 kepala keluarga lain terpaksa mengambil uang ganti rugi atas lahan dan rumah yang digusur. Sebagai tulang punggung keluarga, janda empat anak itu mencoba realistis.
“Lahan sudah habis. Rumah gak punya. Aku harus menghidupi anak-anak yang butuh makan dan biaya sekolah,” kata Tuginah.
Ada 10 petak lahan warisan orang tua yang dikenai ganti rugi untuk enam bersaudara. Tuginah mengelola empat petak bersama kakaknya. Namun proses pemberian ganti rugi tak berjalan mulus. Petugas pengukuran melakukan kesalahan. Khusus petak sawah miliknya dicatatkan menjadi milik orang lain. Proses mediasi sengketa itu masih bergulir di Pengadilan Negeri Wates. Hakim belum menghadirkan para pihak untuk merampungkan bersama.
“Mestinya 30 Maret 2020 lalu. Karena corona, pengadilan menunda sampai waktu tak ditentukan,” kata Tuginah.
Meski mengambil uang ganti rugi, mereka minta AP untuk membiayai pembangunan rumah mereka yang digusur paksa. Hasilnya, AP bersedia. Asalkan warga menyediakan lahan terlebih dulu. Proses pembangunannya pun ditentukan AP. Warga tinggal terima kunci. Dari 25 kepala keluarga, dua KK yang menolak karena sudah punya rumah di tempat lain.
“Ini tali asih pihak bandara yang telah merobohkan rumah kami. Ini pun pakai debat. Padahal hak warga,” kata Tuginah.
Pemerintah pun mengklaim bisa membuat warga terdampak bandara hidup lebih sejahtera. Bagi Tuginah, warga sejahtera jika diberi modal lahan pertanian. Mengingat latar belakang mereka adalah petani.
“Kalau bertani, lansia pun tetap bisa bekerja. Cabut rumput, nanam cabai, manen cabai,” kata Tuginah.
Sejak awal, Tuginah telah berhitung. Sebagai petani, ia harus bisa mendapat lahan garapan pengganti. Beruntung ada warga menjual lahan luas. Ia dan kakaknya membeli masing-masing seluas 1.760 meter persegi. Di atas lahan seluas 450 meter persegi didirikan rumah yang dibangun AP. Sisanya sekitar 1.200 meter persegi digunakan untuk menanam cabai. Hamparan tanaman cabai berpagar kangkung itu memanjang dari samping rumah hingga ke belakang.
“Hidup sebagai petani, yang penting punya lahan,” kata Tuginah.
Sudah setahun, ia tinggal di sana. Sekali panen cabai pernah mencapai 5,5 kuintal dengan harga Rp10 ribu per kilo. Hasil panennya ditampung pengepul. Tapi sejak pandemi COVID-19, harganya anjlok jadi Rp 5.000-Rp 7.000 per kilo. Seikat kangkung dari Rp10 ribu turun jadi Rp5 ribu.
Bedanya, sebelum digusur bandara, ia butuh beberapa menit untuk sampai ke lahannya. Kini, begitu buka pintu langsung disambut hamparan tanaman cabai. Airnya pun jernih dari sumur sedalam 10-12 meter. Sementara di lahan lama, ia mesti butuh beli solar untuk menghidupkan mesin diesel yang menyedot air untuk mengairi lahan.
Di sisi lain, lahan yang dibelinya kini tak bisa ditanami padi. Roda pertaniannya yang dulu berputar antara beras dan cabai tak pulih. Meski saat ini, ia berlega hati karena masih menyimpan berkarung-karung gabah sisa panen masa sebelum penggusuran. Itu pun hanya bertahan 1-1,5 tahun untuk memberi makan anak-anaknya. Setelah itu, siap-siap beli beras.
“Sekarang bagaimana caranya aku bikin kehidupan lagi. Hidupi anak, biar bisa sejahtera lagi,” kata Tuginah.
3. Rutinitas perempuan petani yang hilang

Hingga kini, Sofyan dan istrinya Mulatmi, 34 tahun, tetap menolak mengambil uang ganti rugi. Usai Masjid Al Hidayah yang menjadi bangunan terakhir digusur, mereka tinggal di tenda bekas lokasi masjid selama enam bulan. Hingga akhirnya mereka dan orang tuanya terdampar di rumah milik saudara di Kecamatan Kokap. Pemiliknya tinggal di luar kota. Sampai sekarang, Sofyan tak tahu status rumah yang ditempatinya: pinjam atau diberi.
Mereka memutar otak untuk menyewa lahan pertanian. Letaknya jauh dari rumah, yaitu Pleret, Kecamatan Panjatan yang butuh 30 menit naik motor ke sana. Harga sewa sepetak lahan senilai Rp 2,5 juta per tahun yang dibayar dari sisa pemberian donasi. Lahan itu ditanami semangka yang hasil panennya untuk menyewa lahan baru. Kini mereka menyewa tiga petak. Ditanami semangka dari 12 bungkus biji semangka. Sebungkus berisi 450 biji. Dalam setahun bisa 3-4 kali panen dengan mengantongi Rp26 juta sekali panen.
“Dulu, di lahan sendiri, hasil panen bisa dua kali lipat sekarang,” kata Sofyan.
Kini, Rp26 juta tak bisa utuh dibawa pulang. Mesti dipotong sana sini untuk menambal biaya. Dulu, biaya perawatan hingga panen tak sampai Rp1 juta. Mengingat tenaga kerja diolah sendiri bareng istrinya. Kini, mereka mesti mengeluarkan Rp1,5 juta untuk biaya menyiram, biaya tenaga kerja Rp 8 juta kali untuk dua orang. Belum ditambah biaya makan selama dua bulan dan transportasi.
Sebelum digusur, mereka juga bisa menanam cabai dan aneka sayuran lain. Mulatmi ingat, ketika harga cabai mencapai Rp100 ribu per kilo, mereka bisa mengantongi Rp 500 ribu dalam dua hari. Sayuran yang ditanam seperti gambas, kacang panjang, kangkung, tomat bisa dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual.
“Orang tani kan penghasilan sedikit-sedikit, tapi terus. Nabungnya juga sedikit-sedikit dan ajeg,” kata Mulatmi.
Kini, lahan sewa yang lokasinya jauh itu hanya ditanami semangka. Tak lagi menanam sayuran dan cabai. Sayuran untuk sehari-hari harus beli. Uang pun dikeluarkan secara rutin untuk biaya dua anaknya yang bersekolah di pesantren di Sleman. Otomatis, kesempatan menabung menipis.
“Sekarang lebih berat. Uangnya mesti buat keluarga, terus buat sewa lahan. Harus irit,” papar Mulatmi.
Lantaran jauh pula, Mulatmi tak bisa saban hari pergi bertani. Biasanya pagi hari usai mengantar si bungsu sekolah, ia mampir ke lahan. Sementara sekolah anaknya di Jaten butuh 30 menit juga dari rumah. Siang hari pulang sembari menjemput anak. Ia pun tak sempat lagi menjual makanan ringan ke Pasar Glagah seperti dulu. Sedangkan suaminya berangkat pagi, pulang petang. Ketika bertani di lahan sendiri, Mulatmi seharian bergumul dengan lahan pertanian. Bahkan sempat mengajar PAUD di Masjid Al Hidayah pagi hari. Sementara sore hari, suaminya yang mengajar TPA.
“Hilang rutinitas ke lahan. Kalau senggang saja. Kegiatan tambahan juga gak ada. Yang utama ngurusin anak,” kata Mulatmi.
Tak hanya Mulatmi, orang tuanya yang lansia pun menjadi korban. Di tanah kelahiran, mereka masih bisa bertani dan memelihara kambing. Cukup puas karena punya penghasilan sendiri. Kini hanya bisa menghabiskan waktu tanpa aktivitas di rumah.
“Rata-rata seusia bapak ibu nganggur. Banyak lansia jadi korban,” kata Sofyan.
Dua temannya yang masih menolak ganti rugi juga banting setir. Ada yang bekerja jadi tukang parkir di objek wisata Pantai Glagah. Ada yang jadi buruh ayam potong. Perekonomian yang mencekik membuat mereka memperlakukan sama atas istri dan anak-anaknya.
“Mereka titipkan kepada orang tua masing-masing,” kata Sofyan.
4. Hidup menganggur di relokasi

Relokasi Palihan terletak sekitar satu kilometer dari bandara. Ada 99 KK yang masuk rombongan awal penerima uang ganti rugi tinggal di lahan bekas tanah kas desa itu. Tiap KK dapat jatah tanah seluas 200 m2 yang harus dibeli seharga Rp500 ribu per meter persegi. Belum lagi tiap KK mesti merogoh kocek untuk biaya bangun rumah.
Wajah lokasi relokasi di sana tak beda dengan kompleks perumahan di perkotaan. Rumah-rumah minimalis, berdempetan, cat warna warni, berhalaman sempit, dan sebagian bermobil. Aneka tanaman hias mempercantik di sudut-sudut ruang tersisa. Jauh beda dengan potret rumah mereka dulu yang berhalaman luas dan ditumbuhi pepohonan tinggi. Kelapa, durian, melinjo, petai. Siang itu, IDN Times sempat menyambangi sejumlah perempuan yang tengah berkumpul di rumah salah satu warga untuk arisan. Sebagian menyambut ramah, sebagian lagi menatap curiga.
“Ibu-ibunya 80 persen nganggur. Sebagian kecil buka warung, salon. Bapak-bapaknya ya mburuh di proyek,” kata Kepala Dukuh Kragon II, Desa Palihan, Wiharto, 54 tahun saat ditemui di rumahnya.
Ada yang bergantung bunga deposito bank dari sisa uang ganti rugi. Sungguh jauh beda dengan kehidupan sebelum digusur yang diwarnai kesibukan di lahan pertanian.
Pemilik salon, Anik Suparsih, 42 tahun misalnya. Dulu, suaminya juga mengolah lahan cabai. Kecuali beras, sayuran seperti tomat, terung, kacang panjang tinggal petik. Anik pun turut menyokong penghasilan rumah tangga dari usaha salon.
Lalu mereka menempati relokasi yang disediakan dua tahun lalu. Penempatan rumahnya berdasarkan lotre. Rumahnya di sisi depan dari hasil konsinyasi Rp1,8 miliar. Uang itu ganti rugi atas sepetak rumah, halaman, dan lahan pertanian seluas 1.000 m2 milik ibu mertuanya. Hasilnya dibagi enam bersaudara. Dua rumah baru di sana dibangun milik suami dan ibu mertua. Anik juga bisa beli dua mobil bekas, untuk pribadi dan disewakan.
“Juga bisa bikin salon. Kalau dulu kan nyewa tempat di pasar,” kata Anik.
Meski terkesan mewah, perekonomiannya morat-marit. Uang ganti rugi sudah ludes. Padahal apa-apa serba beli. Dalam sehari mesti menguras kocek Rp30 ribu-Rp35 ribu untuk beli sayur. Juga membeli air mineral isi ulang karena air sumur menguning. Kemudian mencicil Rp1 juta per bulan selama empat tahun dari kredit bank Rp30 juta untuk membangun salon. Membayar pajak rumah Rp115 ribu per tahun untuk rumah tipe 36. Sementara, suaminya menganggur. Hasil rental mobil cepat habis untuk urusan bengkel. Mau tak mau keuangan menggantungkan dari usaha salon yang hanya Rp150 ribu-Rp200 ribu per hari. Pelanggannya adalah para pekerja proyek bandara.
“Kalau nanti proyek sudah selesai, ya sepi. Kalau di pasar dulu kan ramai,” kata Anik.
Kondisi Indarwati lebih ngenes lagi. Sebelum penggusuran, ia kerja di pabrik sepatu di Tangerang selama sembilan tahun. Pulang ke Palihan dan bikin rumah. Untuk menambal kebutuhan sehari-hari, ia menjadi buruh menanam dan memetik cabai. Ketika harga cabai tinggi, Indarwati bisa dapat upah Rp 100 ribu per hari. Saat harga murah, upah pun turun jadi Rp 40 ribu per hari. Ia juga bisa beternak ayam dan kambing. Hanya bertahan empat tahun, usai itu kena gusur.
Indarwati pindah ke relokasi yang sama dengan Anik. Lantaran hanya punya rumah kecil tanpa lahan pertanian, ganti rugi yang didapat juga kecil. Rp189 juta saja. Uang itu hanya bisa buat beli lahan 200 m2 senilai Rp117 juta. Untuk bangun rumah dapat tambahan dari orang tua.
Pemasukan hanya mengandalkan upah harian suami yang tengah menjadi pekerja kontrak proyek bandara Rp80 ribu per hari. Jika proyek selesai, keuangan keluarga itu terancam. Upah itu mesti dibagi untuk biaya sekolah si bungsu yang kelas 3 SMP. Si sulung yang lulus SMK dipastikan tak bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Belum lagi biaya untuk kebutuhan sehari-hari.
“Paling berat itu biaya sosial. Untuk hajatan,” kata Indarwati.
5. Janji kerja sebatas iming-iming

Iming-iming warga terdampak akan dapat pekerjaan di bandara hanyalah pepesan kosong. Wiharto ingat, janji itu disampaikan ketika proses sosialisasi bandara.
“Yang petani akan dialihkan kerja ke bandara,” kata Wiharto.
Warga terdampak dipetakan menjadi ring 1, 2, dan 3. Ring 1 adalah warga yang rumah dan lahannya digusur. Mereka dijanjikan dapat prioritas dipekerjakan. Nyatanya tak semudah membalik telapak tangan. Warga mesti mengantongi surat rekomendasi dari desa.
“Ternyata enggak digubris sama AP,” kata Wiharto.
Sejumlah kriteria persyaratan mesti dipenuhi. Umur harus di bawah 37 tahun, pendidikan layak, ditambah syarat tinggi dan berat badan. Tak satu pun warga yang nyantol kerja di sana. Paling banter jadi satpam perusahaan-perusahaan yang menggarap proyek di bandara dengan status kontrak. Jika proyek selesai, kontrak kelar juga.
“Petani enggak bisa komputer. Tapi kalau nyiramin taman, cabut rumput, ngepel lantai, kan mestinya bisa (diterima),” kata Wiharto.
Usia muda pun ternyata bukan jaminan warga terdampak dapat prioritas. Anak sulung Indarwati baru lulus SMK Jurusan Listrik. Dia ikut pelatihan menjadi porter.
“Tapi enggak direkrut. Enggak ada jaminan masuk,” kata Indarwati.
Peluang kerja bagi perempuan lebih sempit lagi. Sempat ada pelatihan kuliner, seperti bikin bakpia, keripik dari daun. Tapi pemasaran sulit. Warga berharap dapat los di bandara untuk menjual produk-produk hasil pelatihan.
“Biaya sewa los Rp75 juta per tahun,” kata Wiharto.
Ada juga pelatihan menjahit dan Bahasa Inggris selama tiga bulan buat warga yang mau. Menurut Wiharto, pelatihan itu kerja sama Angkasa Pura dengan balai latihan kerja (BLK). Namun tak ada tindak lanjut dan manfaatnya. Indarwati menambahkan, peserta pelatihan itu pun dibatasi hanya beberapa orang.
“Buat ibu-ibu yang rata-rata sudah 40 tahunan ini enggak ada pelatihan,” kata Indarwati.
Relokasi Palihan juga pernah kedatangan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN). Mereka datang membawa program pelatihan manajemen keuangan.
“Keuangan apa, wong enggak punya uang,” tukas Anik.
Mulatmi juga sempat mendengar informasi ada pelatihan untuk perempuan terdampak bandara. Seperti pelatihan bikin kue. Entah pihak mana yang mengadakan. Tapi Mulatmi tak ditawari.
“Yang ikut pelatihan hanya yang menerima (pro bandara). Setiap datang pelatihan, kabarnya dapat amplop,” kata Mulatmi.
Seingat Tuginah pun tak diajak ikut pelatihan. Setahu dia, pelatihan Bahasa Inggris buat perempuan muda usia.
“Enggak ada pelatihan untuk ibu-ibu. Sekali pun ada, enggak mau. Enggak sesuai kebutuhan,” kata Tuginah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana membantah ada batasan persyaratan bagi perempuan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan AP maupun BLK, dan sejumlah lembaga lain.
“Bisa kok, jika mau bergerak, mau usaha, mau ikhtiar,” kata Eko.
Sementara General Manager PT AP I Yogyakarta Agus Pandu Purnama, jumlah tenaga kerja dari Kulon Progo yang terserap di Bandara YIA mencapai 60 persen. Data itu berdasarkan survei anggota DPRD DIY. Dan ia membenarkan ada persyaratan kompetensi dan umur untuk bekerja di sana.
“Buktinya dari Kulon Progo yang memenuhi ketentuan dan diterima kan banyak. Juga banyak sektor yang bisa dimanfaatkan,” kata Pandu.
Mengutip data dari Pemkab Kulon Progo, angka pengangguran di sana diklaim turun dari 3,7 persen menjadi 1,4 persen. Persentase itu disebut terendah se-DIY.
Ia juga menyiapkan ruang untuk ruko atau tenant di bandara seluas 1.500 m2 di ruang tunggu keberangkatan bagi 300 UMKM. Mekanismenya diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo dan DIY.
“Bahkan bisa gratis,” janjinya.
6. Pembangunan mesti melibatkan partisipasi perempuan

Selama mendampingi warga terdampak bandara, Pitra turut merasakan potensi konflik yang muncul di sekitar perempuan. Bisa dilihat dari pola produksi dan konsumsinya. Seperti ketika perempuan harus hidup di tenda karena rumahnya digusur. Perempuan tetap harus tanggung jawab memikul rutinitas yang mesti dikerjakan seperti ketika rumah masih berdiri. Dengan kondisi keuangan seminim yang ada, perempuan tetap harus ke pasar, memastikan keluarga bisa makan, anak bisa sekolah, menyisihkan biaya sosial.
“Bahkan bukan pengeluaran harian yang membengkak. Tapi cara berinteraksi,” kata Pitra.
Semisal untuk sumbangan hajatan warga. Lantaran meski telah terpecah antara pro dan kontra bandara, toh relasi sosial tak mau tercerabut dari akarnya.
“Dan semua itu lebih dipikirkan perempuan ketimbang laki-laki,” kata Pitra.
Kondisi tersebut, Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Defirentina One Muharomah mengimbuhkan, adalah gambaran konstruksi sosial, bahwa perempuan juga bisa mencari nafkah, jadi pengambil putusan, jadi pemimpin. Tak hanya laki-laki. Tapi berhadapan dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban.
“Karena invisible (tidak terlihat),” papar One.
Perempuan jarang dilibatkan dalam proses-proses pembangunan itu. Baik invisible dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan. Setidaknya ada empat kata kunci agar pembangunan infrastruktur adil bagi perempuan. Pertama, akses. Perempuan dapat menggunakan hak dan sumber daya secara bersama. Kedua, partisipasi. Perempuan dilibatkan sejak awal proses pembangunan. Ketiga, kontrol. Perempuan punya kekuatan untuk mengambil putusan. Keempat, manfaat. Perempuan mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan.