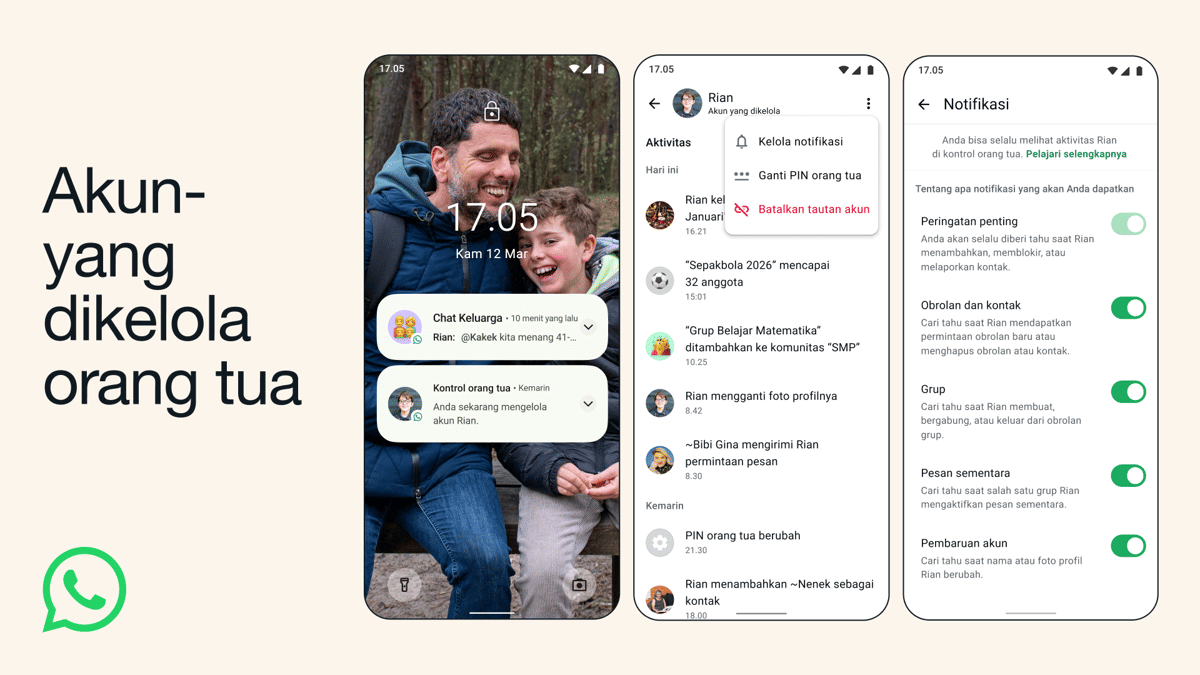Pakar UGM Kritik Rumah Subsidi 18 Meter Persegi: Berisiko Sosial

Ukuran 18 meter persegi hanya cocok untuk hunian darurat, bukan rumah permanen
Risiko kesehatan mental hingga KDRT akibat desain minim dan fasilitas pendukung yang kurang
Rumah susun bisa jadi solusi alternatif dengan akses transportasi publik dan fasilitas umum yang memadai
Rencana pemerintah membangun rumah subsidi seluas 18 meter persegi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memicu reaksi dari berbagai kalangan. Dua pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan kekhawatiran mereka, mulai dari aspek teknis arsitektur hingga dampak sosial yang mungkin timbul.
Secara umum, mereka sepakat bahwa rumah kecil bukan masalah utama selama dirancang dengan matang, tumbuh secara bertahap, dan ditunjang fasilitas memadai. Tanpa pendekatan itu, kebijakan ini justru bisa memunculkan masalah baru, termasuk risiko kemiskinan struktural. Berikut ini beberapa catatan penting dari pakar UGM terkait wacana rumah subsidi 18 meter persegi.
1. Luas 18 meter persegi hanya cocok untuk hunian darurat, bukan rumah permanen

Pakar Teknik Arsitektur UGM, Ir. Ikaputra, mengatakan rumah berukuran 18 meter persegi adalah standar minimum internasional untuk hunian darurat, misalnya untuk korban bencana. Jika ukuran ini diterapkan sebagai rumah permanen, maka harus dibarengi dengan konsep rumah tumbuh yang jelas dan terencana.
“Kalau digunakan untuk jangka panjang, perencanaannya harus jelas. Jangan sampai niat baik malah menghasilkan kawasan padat dan tidak layak,” kata Ikaputra dalam keterangannya dilansir laman resmi UGM.
Masalah utamanya bukan di ukuran rumah, tapi di luas lahan yang disiapkan. Jika hanya 25 meter persegi, ruang untuk pengembangan hampir tidak ada. Idealnya, lahan minimal 50 meter persegi agar rumah bisa tumbuh sesuai kebutuhan keluarga dan tetap menyisakan ruang terbuka hijau.
2. Risiko kesehatan mental hingga KDRT

Sementara dari sisi sosial, pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) UGM, Nurhadi, menilai bahwa rumah kecil dengan desain minim berisiko menciptakan kemiskinan baru jika tak disertai kualitas hunian dan fasilitas pendukung.
"Rumah bukan sekadar tempat berlindung, tapi tempat hidup bermartabat. Kalau terlalu sempit dan tak layak, ini bisa berdampak pada kesehatan mental hingga KDRT, terutama bagi ibu dan anak," ujar Nurhadi.
Ia juga menekankan bahwa penyediaan rumah harus dibarengi fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan akses ke pekerjaan. Jika tidak, rumah subsidi malah bisa menambah beban sosial baru.
3. Rumah susun bisa jadi solusi, asalkan terintegrasi

Kedua pakar UGM sepakat bahwa rumah susun (rusunawa) bisa jadi alternatif lebih rasional, terutama di wilayah perkotaan dengan lahan terbatas. Namun, pembangunan rumah susun harus diiringi dengan akses transportasi publik dan fasilitas umum yang memadai.
“Kalau dibangun di pinggiran kota, harus ada akses mudah ke tempat kerja." kata Ikaputra.
Nurhadi menambahkan, rumah susun yang dikelola dengan baik bisa menciptakan ruang komunal dan kehidupan sosial yang lebih sehat, ketimbang menumpuk warga berpenghasilan rendah dalam blok-blok rumah kecil tanpa ruang terbuka.
Pandangan dua pakar UGM ini menjadi pengingat penting bahwa hunian layak tak cukup hanya soal kuantitas. Rumah yang terlalu kecil, minim fasilitas, dan tidak berkembang justru bisa menambah masalah sosial di masa depan.
Bagi generasi muda, terutama kaum milenial yang sedang mencari hunian pertama, desain rumah yang layak, tumbuh, dan sehat secara mental menjadi kebutuhan nyata. Kebijakan rumah subsidi seharusnya tak hanya menjawab kebutuhan memiliki rumah, tapi juga memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar layak untuk ditinggali dan ditumbuhkembangkan.