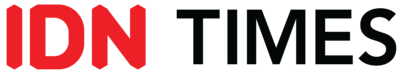Mereka yang Melawan Stigma COVID-19: Harus Berani Bersuara
 Ilustrasi. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times – Hingga kini, sejumlah daerah di Indonesia dihebohkan jenazah pasien positif COVID-19 diambil paksa keluarganya. Di daerah lain, sejumlah pasien yang terinfeksi virus corona menolak dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Beberapa pasien yang diisolasi di rumah sakit pun memilih kabur. Tak terkecuali kasus-kasus tenaga kesehatan (nakes) yang dikucilkan warga di lingkungannya.
Dua hari lalu, 9 Juli 2020, puluhan pedagang Pasar Gatak, Kabupaten Bantul libur berjualan. Alasan beragam, mulai dari sakit sampai banyak urusan. Diketahui alasan utama cuma satu, menghindari rapid test massal yang digelar untuk pedagang di sana. Mereka takut, jika hasilnya reaktif, hingga dinyatakan positif corona, maka warga akan mengucilkannya. Hal ini adalah bukti bahwa stigma masih jadi persoalan sejak awal pandemik.
“Yang terinfeksi corona bukanlah pesakitan. Siapa saja bisa terinfeksi,” kata relawan Lapor COVID-19, Ahmad Arif saat membuka diskusi webinar bertema Melawan Stigma, Memutus Corona yang digelar pada 9 Juli 2020.
Semestinya, masyarakat bersolidaritas memberikan dukungan dan bantuan terhadap pasien dan keluarganya agar sembuh. Seperti yang dialami penyintas dari Kampung Balirejo, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Ndaru Triatmoko. Dia tertular virus dari klaster Indogrosir di Sleman usai menolong temannya yang pingsan pada 18 April 2020. Yang menarik, warga di kampungnya tak mengucilkan keluarga yang ditinggalkan selama diisolasi di rumah sakit. Mereka justru memberikan bantuan sembako berupa sayuran dan lauk pauk. Mengingat keluarganya juga menjalani isolasi mandiri 14 hari.
“Sehari tiga kali dikirim,” kata Ndaru dalam cuplikan video yang diputar menjelang diskusi.
Dan ketika Ndaru dinyatakan sembuh, dia mendapat sambutan dari warga setiba di kampungnya. Sambutan drum band hingga tumpeng nasi kuning. Stres yang dirasakan Ndaru selama isolasi 46 hari tanpa melihat matahari, lenyap sudah.
“Jadi warga mikirnya bukan aib. Tapi bagaimana memberi dukungan. Kalau jenengan jadi saya pasti terharu,” kata Ndaru.
Sayangnya, tak semua penyintas mendapat perlakuan sama seperti Ndaru. Tak semua warga bersikap positif terhadap warga yang terinfeksi.
“Sudah sakit, diisolasi, pulang dihindari. Coba yang menghindari itu disuruh merasakan, pasti stres,” tukas Ndaru.
Baca Juga: [UPDATE] Terus Bertambah, Kasus Positif COVID-19 di DIY Jadi 370
1. Diusir dari kos karena sakit dan mengisolasi diri
Sembilan hari pada awal Maret 2020, Meika Arista mengunjungi sejumlah kota di Indonesia. Setiba di Surabaya pada 10 Maret 2020, kondisi tubuhnya drop. Dia memaksakan diri kembali ke Jakarta dengan pesawat terbang yang sudah dibeli tiketnya.
Istirahat di kos tak membuat kesehatannya membaik. Dengan diantar teman, Meika memeriksakan kondisinya ke rumah sakit terdekat.
“Leukosit saya tinggi. Kemungkinan besar sedang ada virus yang menyerang,” kata Meika, warga terdampak stigmatisasi menirukan perkataan dokter dalam diskusi webinar.
Dokter meminta Meika istirahat tiga hari di kos. Tak perlu rawat inap. Namun kondisinya yang memburuk mendorongnya pergi ke rumah sakit swasta yang dinilai lebih baik. Dokter dengan lugas mengatakan Meika harus dirujuk ke rumah sakit rujukan corona terdekat.
“Saya deg-degan. Apakah benar-benar saya terinfeksi corona?” tanya Meika.
Di meja registrasi rumah sakit rujukan, Meika mengisahkan riwayat perjalanan dan gejala yang dirasakan. Namun tak ada tindakan medis yang dilakukan dokter di sana. Sekadar cek tensi darah dan suhu tubuh pun tidak.
“Saya dikatakan bukan pasien yang urgen untuk ditangani,” kata Meika.
Meika menelan kekecewaan sendiri di tengah rasa sakit yang mendera. Berbekal obat yang diberikan tanpa pemeriksaan medis, Meika pulang. Untuk langkah antisipasi, dia mengisolasi diri di kos.
Pada hari ketujuh, kondisinya membaik. Dia membuat petisi ditujukan presiden dan menteri kesehatan melalui Change.org tentang perlunya tes massal. Lewat media sosial, petisi itu disebar. Orang lain pun ikut membantu menyebarkan. Salah satu warga yang mengetahui petisi itu berulah. Berbekal update status yang dibuat Meika di akun medsosnya, orang itu menyebarkan informasi ke WAG warga kampung setempat. Bahwa orang bernama Meika, dengan alamat lengkap kos dan pekerjaan advokat adalah orang positif corona. Padahal tiga rumah sakit yang didatangi Meika, belum satu pun memastikannya terinfeksi corona.
Kampung setempat pun heboh. Banyak yang menelepon dirinya dan pemilik kos untuk memastikan kebenaran informasi itu.
“Alhamdulillah, ibu kos orang yang berpendidikan, paham dan mengikuti perkembangan virus corona di Indonesia,” kata Meika.
Komunikasi yang baik dijalin dengan pemilik dan penghuni kos. Seperti permintaan Meika agar mereka tak menyentuh gagang pintu kamarnya. Meika pun mendapat kamar mandi tersendiri selama dia mengisolasi diri. Untuk makan pun, Meika memesan melalui ojek online dan pemilik kos membawanya ke depan kamar. Sikap dukungan itu cukup membantunya menghadapi sikap tak bersahabat di lingkungan warga.
Hingga suatu malam, Meika ditelepon seorang warga setempat yang memaksanya menunjukkan surat bebas corona. Jika tidak ada, Meika mesti angkat kaki dari kosnya demi melindungi warga sekitar dari kemungkinan penularan. Kisah Meika yang telah berupaya mendatangi tiga rumah sakit tak diterima. Sementara malam terus beranjak sekitar pukul 10 lebih. Meika menangis, tertekan, mengingat tak ada sanak saudara di Jakarta.
“Saya harus ke mana? Apa mungkin saya ke Yogyakarta malam itu juga,” kenang Meika sedih.
Teman-temannya pun datang malam itu untuk mengadvokasi. Warga yang mengancamnya minta digelar pertemuan.
“Saya heran. Saya dikira positif corona, tapi warga malah minta ketemuan,” kata Meika yang mengaku belum menjalani pemeriksaan tes swab sama sekali.
Tiga hari kemudian, Meika diundang dalam pertemuan tingkat RW. Warga yang menyebarkan hoaks pun diundang. Orang itu diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan karena menyebarkan informasi tak benar. Surat pernyataan yang dibuat menyebutkan ulahnya menyebarkan kabar Meika positif corona hanya iseng. Alasannya, bentuk kepedulian atas penyebaran virus corona di Indonesia. Namun ulahnya malah bikin warga gaduh. Sejumlah warga yang hadir pun mengaku takut dengan kabar itu.
“Kalau sakit memilih tak ke rumah sakit. Takut kalau diusir dari kos karena dikira corona,” kata Meika.
Bahkan ketika ada ambulans datang, warga riuh. Was-was ada yang sakit. Padahal ambulans itu datang untuk mengusung karpet yang dicuci di laundry. Dalam pertemuan itu pun Meika baru tahu ada warga yang menggelar ritual di depan kosnya. Mereka menyebar bunga dan merapal jampi-jampi.
“Ini kan salah kaprah. Orang sakit mestinya ditolong, bukan dibikin mistis,” kata Meika.
2. Dinyatakan sembuh usai empat kali hasil tes swab negatif
Hasil rontgen kedua paru petugas laundry rumah sakit di Kediri tampak memutih. Namun tak ada perintah pihak rumah sakit setempat untuk membawanya ke rumah sakit rujukan demi menegakkan diagnosis. Justru dia disuruh pulang dan kontrol di puskesmas terdekat. Dokter di unit gawat darurat setempat, Tri Maharani kaget. Dia menduga 80 persen gejala awalnya merujuk COVID-19. Lantaran kondisinya parah, Tri berinisiatif membawanya ke rumah sakit kota terdekat. Dan petugas laundry itu pun diketahui positif corona.
“Ini adalah risiko pekerjaan menjadi dokter. Tapi tak semudah yang dibayangkan masyarakat. Dari situlah stigma itu dimulai,” kata Tri mengisahkan awal mula stigmatisasi yang menimpanya usai didiagnosis positif COVID-19 dalam diskusi.
Diagnosis awal menunjukkan Tri menderita pneumonia. Paru kirinya tampak blur. Sebagai dokter yang sebelumnya menjadi relawan di rumah sakit paru di Jakarta, dia paham betul dampak penyakit itu.
“Maut. Dan saya tahu berada antara hidup dan mati,” kata Tri yang sering menangani pasien korban gigitan ular berbisa, sengatan ubur-ubur.
Dia pun dijemput untuk menjalani isolasi di rumah sakit. Saat keluar rumah, dia melihat perangkat RT dan RW, lurah, satuan polisi pamong praja, juga polisi ada di depan rumah. Keluarganya tak dibolehkan ke luar rumah untuk melakukan isolasi mandiri.
Yang bikin kecil hati ketika salah satu pembesar di kotanya mengumumkan penyakitnya di radio. Banyak juga orang yang menelepon dan menanyakan mengapa dirinya yang seorang dokter bisa terinfeksi virus itu.
“Sebenarnya itu pertanyaan biasa. Tapi bagi saya seperti ditusuk,” kata Tri.
Pertanyaan itu dirasa Tri menyangsikan prosedur pengamanan kesehatan yang telah dilakukan. Pun seolah menudingnya sembrono bertugas. Padahal dia mengenakan APD lengkap dengan masker N95 atau level III. Sementara WHO baru saja mengumumkan hasil penelitian yang memungkinkan penularan COVID-19 melalui aerosol atau udara.
“Enggak cukup N95. Harusnya APR yang Rp 47 juta itu,” tukas Tri.
Selama 10 hari, Tri menjalani isolasi di rumah sakit. Dukungan pun datang mengalir. Dia mendapat kiriman bunga papan dari anggota dewan. Ada pesan tertulis yang membuat semangatnya bangkit. Cepat sembuh dokter, Indonesia membutuhkanmu.
“Itu bikin semangat saya yang down terus melambung. Saya tak boleh mati karena COVID. Banyak hal harus saya lakukan,” kata Tri bertekad.
Rasa sakit akibat virus itu dilawannya. Mual, batuk, nyeri. Sekadar minum susah. Bicara pun sulit. Anjuran bagi orang sakit untuk banyak makan dan berpikir positif diakui Tri sangat sulit. Untuk mengobati pneumonia, dia mesti menahan nyeri ketika mendapat suntikan antibiotik berupa cairan kental sebanyak dua botol besar.
Hingga akhirnya empat kali tes swab terakhir menunjukkan hasil negatif berturut-turut. Biasanya, cukup dua tes swab dengan hasil negatif bisa menjadi tiket pulang. Tri mesti memastikan empat kali negatif. Diantar tim dengan mobil ambulans, Tri pulang ke rumah. Pihak RT dan RW yang ditunggu tim tak kunjung datang. Alasannya tengah mengikuti rapat. Dan mereka baru datang ketika tim pulang.
“Rupanya mereka takut karena tim datang dengan APD lengkap. Dan naik ambulans,” kata Tri.
Dan stigma itu tak kunjung usai. Tri telah menjalani isolasi mandiri 14 hari lebih usai pulang dari rumah sakit. Dia juga usai pulang dari kontrol selama dua hari. Hari ini, 11 Juli 2020, dia berencana masuk kerja. Namun dia dapat pesan singkat dari rumah sakit yang memintanya untuk isolasi kembali 14 hari lagi. Tri merasa api semangat yang dijaganya agar terus membara, tiba-tiba dipadamkan lagi.
“Bukankah saya sudah 14 hari lebih isolasi mandiri? Mengapa orang-orang medis justru bikin takut? Mestinya dukung saya biar semangat dan bisa kerja lagi,” tukas Tri kesal.
Bagi Tri, dampak stigmatisasi itu berat. Lantaran dilakukan oleh orang-orang yang tak tahu, tapi pura-pura tahu.
“Dan ketika stigma terjadi di dunia medis, lebih berat lagi,” kata Tri.
3. Stigmatisasi akibat informasi tak akurat dan tak berdasar fakta
Peneliti psikologi sosial Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Dicky Pelupessy menjelaskan, stigmatisasi dampak dari informasi yang bias. Seperti informasi yang tidak memadai, tak merata, tak terjangkau, tak akurat. Baik berupa gosip atau pun hoaks yang diproduksi sumber informasi. Orang menganggap COVID-19 adalah aib. Orang yang terinfeksi tak bisa disembuhkan dan berujung kematian. Mereka takut dan cemas jika mati akibat tertular. Sedangkan mereka ingin hidup lebih lama lagi.
“Padahal peluang pasien COVID-19 untuk sembuh itu ada,” kata Dicky.
Orang pun melakukan stigmatisasi dengan mengucilkan, mengusir, merisak, baik terhadap pasien, mantan pasien, keluarga pasien, keluarga mantan pasien, termasuk juga nakes. Akibatnya, pasien akan berusaha menghindar, jika ada tes massal. Menyembunyikan diri, jika sakit. Kabur dari rumah sakit ketika menjalani isolasi. Lantaran mereka takut mendapat stigma. Kondisi itu justru menyulitkan situasi. Pasien tak bisa dirawat dan peluang untuk menyembuhkan juga kecil.
“Solusinya adalah perlu ada keterbukaan informasi dan edukasi masyarakat,” kata Dicky.
Bahwa ada orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), juga positif corona di sekitar masyarakat. Selain itu, juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang bisa diterima dan tak bisa diterima masyarakat. Informasi yang diberikan berdasarkan fakta sehingga tak membingungkan.
“Perlu peran komunikator. Tak hanya dari otoritas, tapi yang punya pengaruh. Termasuk dari penyintas,” kata Dicky.
Menurut Meika Arista, stigma lahir ketika seseorang dalam posisi lemah berhadapan dengan orang lain yang merasa superior yang melakukan tindakan yang melemahkan. Informasi sesat yang disebarkan akan membuat publik ketakutan sehingga memunculkan stigma. Dia pun mendukung perlunya payung hukum untuk menangani maraknya stigma dalam masyarakat. Di sisi lain, sebagai individu pun harus berani melawan stigma itu. Meika berbagi resep untuk mengatasinya dengan berani meluruskan informasi yang salah.
“Caranya mencegahnya gimana? Harus berani speak up, bersuara,” kata Meika.
Sebagai penyintas, Tri Maharani pun membagikan tips kepada masyarakat untuk membantu memberikan semangat agar sembuh. Bukan dengan melontarkan pertanyaan atau hal-hal yang menyinggung perasaan pasien. Kok kamu bisa tertular, misalnya.
“Kecuali pasien cerita sendiri. Kalau dia enggak ngomong, jangan paksa bicara,” kata Tri yang berencana menggalang gerakan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para pasien COVID-19.
“Stigma negatif itu harus dilawan. Itu yang bikin orang mati. Bukan karena COVID,” tukas ahli toksinologi itu memungkasi.
Baca Juga: Sampai Madura, Orang Positif COVID-19 Tak Langsung Jalani Perawatan