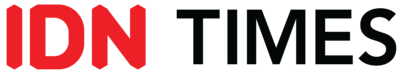Kaum Difabel dalam Lingkaran Stigma Reproduksi dan Seksualitas (1)
 IDN Times/Pito Agustin Rudiana
IDN Times/Pito Agustin Rudiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times — Salah satu hak difabel tercantum dalam Pasal 24 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention of Rights on Persons with Disabilities/UNCRPD) yang telah diratifikasi Indonesia pada 2011, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Hak tersebut juga diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Undang-undangnya belum mengatur detail. Sedangkan perdanya belum ada aturan pelaksananya,” kata Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Nurul Saadah Indriani saat ditemui IDN Times di Kantor SAPDA, Yogyakarta, 27 September 2019.
Sementara berdasarkan data Dinas Sosial DIY pada 2012 yang dikutip dari Laporan Base Line Survey tentang Pemahaman atas Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja dengan Disabilitas di Indonesia menyebutkan sebanyak 24.633 difabel di DIY membutuhkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan seksual.
Persoalannya, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang diberikan di sekolah luar biasa (SLB) terbatas materi dan gurunya. Dan tak semua difabel pernah atau sedang mengenyam pendidikan di bangku SLB. Artinya, tidak semua difabel mempunyai pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Pengetahuan yang diharapkan didapatkan dari keluarga dan lingkungan sosial terkendala stigmatisasi dan budaya tabu yang masih berlaku.
“Padahal difabel menjadi target kekerasan seksual dan perilaku seksual yang tidak aman,” kata Nurul.
Kondisi tersebut, menurut Koordinator Divisi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi SAPDA, Rini Rindawati, menunjukkan adanya pelanggaran hak difabel untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Lantas persoalan apa saja yang rentan dipahami anak dan perempuan berkebutuhan khusus yang kurang atau tidak mendapatkan pengetahuan tentang kespro dengan tepat dan benar?
1. Bocah autis yang suka tiba-tiba menghilang
Pintu rumah di kawasan Depok, Sleman terbuka. Diva, 11, bocah tinggi dan kurus masuk dengan senyum lebar. Ibunya, Tri Sumarni menyambutnya dengan senyum dan pelukan. Perempuan tengah baya yang mengantarnya pun pamit pulang. Usai berganti baju, dengan sekotak makanan dan mencomot dua sisir pisang rebus, Diva masuk kamar. Tri pun menutup pintu kamar dan menguncinya dari luar.
“Dia suka menghilang. Melarikan diri, pergi, lari,” kata Tri saat ditemui IDN Times di kediamannya, 24 September 2019 lalu.
Diva adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Baik Diva maupun anak kedua, Anggita, 12, sama-sama autis dengan gangguan sensorik integratif yang derajat keparahannya berbeda. Diva suka pergi tiba-tiba tanpa ada yang tahu dan tanpa mampu meninggalkan pesan atau sekadar meminta izin. Tri seringkali dibuat pusing karena harus mencari tanpa diketahui lokasinya.
“Anak saya non verbal. Awalnya saya marah-marah kalau dia hilang. Lama kelamaan saya cuma ketawa,” kata Tri yang mau tak mau harus mengawasi Diva 24 jam.
Anggita sudah mulai naksir lawan jenis. Kakak kelas Diva ada yang menaksirnya. Dan Tri dibuat syok mendapati kedua anaknya sudah menstruasi. Bebannya sebagai ibu berasa bertambah. Terhadap Anggita, Tri cukup memberi contoh cara memasang pembalut secara berulang-ulang hingga bisa dimengerti dan ditiru. Sementara Diva suka membuang pembalut yang dikenakannya.
“Gangguan sensorik integratifnya berat,” papar Tri.
Jika dikenakan baju atau barang yang dilekatkan pada tubuhnya dan membuat risih, dia akan Mencopot dan membuangnya. Sekadar memilih seragam yang nyaman dikenakan pun butuh waktu lama. Kondisi itu membuat Tri was-was mengingat Diva suka pergi tiba-tiba tak tahu arah.
“Saya juga tidak tahu ketika dia pergi bertemu siapa dan apa yang dilakukan. Dia kan gak bisa bercerita (non verbal),” kata Tri yang khawatir anaknya menjadi sasaran tindak kejahatan seksual.
2. Tunanetra alami terbalik memasang pembalut
Dewi, sebut saja demikian, 32, adalah guru asal Bantul yang tunanetra total sejak lahir. Beruntung ibunya tidak tabu membicarakan soal kesehatan reproduksi dengan Dewi. Seperti ketika Dewi menstruasi pertama kali usia 12 tahun, ibunya pula yang membantu dan mengajarkan memasang pembalut hingga Dewi bisa melakukan sendiri. Ayahnya pun berperan cukup protektif. Ketika mengetahui Dewi diseberangkan jalan oleh orang tak dikenal ketika berangkat sekolah, dia pun memanggilnya sepulang sekolah.
“Jangan mau diseberangkan orang tak dikenal. Apalagi dipegang tangannya,” kata bapaknya.
Persoalan justru terjadi ketika Dewi akan menikah. Keluarga pacarnya tak merestui karena dia buta. Alasannya, Dewi dianggap tak bisa melayani suaminya, tak bisa menyiapkan segala keperluan suami dan anaknya kelak. Tak patah semangat, Dewi pun menemui orang tua pacarnya untuk memberikan edukasi tentang disabilitasnya.
“Tapi mereka tetap menolak. Diajak salaman pun enggak mau,” kata Dewi.
Hhubungan putus. Akhirnya Dewi bertemu calon suami dan keluarga yang mau menerima disabilitasnya. Bahkan calon mertuanya meminta mereka mempercepat perkawinan. Mereka pun menikah.
“Saat berhubungan seksual, suami yang membimbing,” kenang Dewi.
Dia pun hamil. Rupanya mertua menyimpan kekhawatiran cucunya akan terlahir buta juga.
“Mripate melek ora (mata bayinya terbuka/buta atau tidak)?” tanya mertuanya sebagaimana diingat Dewi. Kekhawatiran itu pun tak terbukti lantaran kebutaan bukanlah bersifat genetik atau turunan.
Beragam persoalan remaja tunanetra yang memasuki masa pubertas juga disampaikan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) A Yaketunis Yogyakarta, Sri Andarini Ekaprapti. Ada murid laki-laki berusia 13 tahun yang selalu dimandikan asisten rumah tangganya, padahal dia sudah akil baliq. Andarini memintanya untuk berlatih mandi sendiri agar bisa mandiri. Anak tersebut juga mempunyai kebiasaan mengelus-elus lembaran kalender yang dipajang di dinding rumah.
“Katanya cantik. Padahal dia tak bisa melihat gambar pada kalender itu,” kata Andarini.
Mungkin pernah ada yang memberi tahu gambar di kalender adalah perempuan cantik. Dan entah siapa yang mengajari anak tersebut untuk berimajinasi sehingga cukup merasa senang hanya dengan meraba tanggalan. Ada pula murid laki-laki yang memegang payudara temannya.
Kasus lainnya, ada murid perempuan yang sudah menstruasi. Tetapi dia tidak tahu cara memasang pembalut.
“Pembalutnya dipasang terbalik,” kata guru kesehatan reproduksi, Sri Wahyuni Endarwati yang mengetahui setelah melihat darah berceceran di kelas.
Baca Juga: 6 Tips Menjelaskan Seksualitas pada Anak, Penting untuk Orangtua
3. Tunadaksa ditolak menikah calon mertua
Dua aktivis SAPDA, Nurul dan Rini adalah sesama difabel daksa yang mempunyai pengalaman hampir sama sebagai penyintas. Sehari-hari, mereka membutuhkan bantuan tongkat untuk berjalan. Mereka pernah sama-sama ditolak orang tua pacarnya untuk menikah dengan stigma tidak bisa melayani suami, tak bisa menjadi istri yang baik, dan tak bisa melahirkan. Kalau pun bisa, anak yang lahir akan cacat.
Rini pun pernah mengalami pelecehan seksual. Ada laki-laki yang memegang payudaranya. Secara refleks, dia pun mencekiknya untuk membuat jera.
Tak hanya itu, statusnya yang masih lajang kian menguatkan stigma sosial yang menganggap difabel itu aseksual alias tak tertarik lawan jenis.
“Padahal normal saja. Saya juga bisa,” kata Rini.
Pemahamannya soal hak kesehatan reproduksi dan seksualitas banyak didapatkan dengan membaca majalah dan novel sejak remaja. Bahkan Rini suka berbagi majalah dan novel yang dipinjam dengan ibunya. Sementara ibunya termasuk orang tua yang enggan mengajarkan seksualitas dan kesehatan reproduksi sejak dini.
“Tetapi ibu sangat protektif kepada saya. Kalau malam belum pulang, beliau menunggu saya di depan pintu,” kata Rini.
Sementara Nurul mendapatkan pengetahuan soal kesehatan reproduksi dari ibunya. Terutama ketika menstruasi pertama, bagaimana memasang pembalut dan mengatasi sakit perut ketika haid.
“Tapi soal kenapa tumbuh rambut kemaluan, tidak (diajarkan). Lebih banyak tahu dari pelajaran Biologi di sekolah,” kata Nurul.
4. Rungu wicara yang mudah jatuh cinta
Pada awal 2019, SAPDA mendapat informasi Forum Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Kota Banjarmasin tentang 11 remaja tuli yang dikeluarkan dari SLB karena hamil. Kehamilannya tidak direncanakan (KTD) karena berbagai penyebab, seperti pemerkosaan atau hubungan seksual dengan teman atau pacar. Penyelesaian yang dilakukan keluarga mereka antara lain aborsi paksa, dinikahkan dengan teman atau pacarnya, dan melahirkan tanpa pasangan.
“Meski senang dinikahkan dengan pacarnya, tetapi usia mereka berapa tahun? Masih terlalu muda,” kata Nurul.
Difabel tuli pun mempunyai kecenderungan suka berganti-ganti pasangan. Nurul pernah mendapatkan kasus temannya yang seorang tuli tenyata mempunyai pacar lebih dari satu. Sementara pacar-pacarnya tidak marah meskipun diduakan. Tidak heran banyak difabel rungu wicara yang tertular virus HIV atau pun telah menderita AIDS. Ada juga sesama tuli menikah, tetapi mereka punya pasangan lain di luar pernikahannya.
Andarini yang pernah menjadi guru di SLB B atau rungu wicara mengaku membimbing anak-anak rungu wicara ketika masa pubertas cukup sulit. Dia pernah mempunyai murid tuli yang mempunyai prestasi seni. Saat mengikuti lomba, murid tersebut bertemu dengan murid lain sekolah yang difabel intelektual tingkat ringan.
“Kenalannya ini ganteng. Murid saya enggak mau jauh-jauh darinya. Mau tampil di panggung asalkan kenalannya itu menonton di dekatnya,” kata Andarini.
Kecenderungan difabel rungu wicara yang berkesan mudah jatuh cinta, menurut Nurul karena beberapa faktor. Difabel rungu wicara ada yang menjadi tuli sejak lahir atau pun setelah dewasa. Bagi tuli sejak lahir tentulah mempunyai referensi kosakata yang terbatas. Tidak heran, tuli sejak lahir mengakibatkan bisu karena tidak mampu mendengar suara sejak lahir.
“Akibat kosakata terbatas, tuli sulit memahami kata atau istilah yang komplek,” kata Nurul.
Sebut saja istilah “patah hati”. Maksudnya hati yang patah? Atau pun “jatuh hati”, apakah artinya hatinya jatuh? Sementara bahasa isyarat yang didapatkan di SLB adalah bahasa isyarat dengan kosakata yang sederhana. Ketika di rumah pun menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa isyarat harian yang bisa dipahami antar anggota keluarga.
“Dan orang tua gak mungkin omongin soal payudara, intercourse, penis. Karena akan sulit menjelaskan dengan isyarat. Pakai penterjemah pun sulit,” kata Nurul.
Padahal pemahaman atas kosakata dibutuhkan difabel rungu wicara untuk menginterpretasikannya. Salah satu upaya yang biasa dilakukan adalah menjelaskan dengan media visual, seperti film, foto, atau tayangan melalui televisi dan gadget. Persoalannya, ketika tayangan visual yang mereka lihat tanpa didampingi dan disertai penjelasan, mereka akan salah mengartikannya.
“Orang yang menyatakan sayang diartikan bisa dipercaya. Kalau percaya, mestinya mau dipeluk, dicium, diraba. Itu bagian ikatan mereka,” papar Nurul.
Tak heran, tuli acapkali punya lebih dari satu pasangan. Sementara di kalangan mereka, sikap itu bagian dari wujud rasa sayang itu.
“Itu bukan budaya tuli. Tetapi tuli tidak mempunyai pemahaman yang baik soal seksualitas dan kesehatan reproduksi karena keterbatasan mereka,” kata Nurul.
5. Difabel intelektual menganggap sentuhan orang lain itu biasa karena terbiasa
Anak dengan retardasi mental yang merupakan bagian dari difabel intelektual acap kali dianggap orang yang tak bisa melakukan apa-apa karena kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata normal. Meskipun usia kalender sudah dewasa, tetapi intelektualitasnya seperti anak-anak.
Rini pernah mendapati kasus seorang perempuan difabel intelektual yang terbiasa dimandikan ayahnya sejak kecil hingga berusia 30 tahun. Alasan ayahnya, karena anaknya suka menghabiskan air satu bak dan membutuhkan waktu yang lama untuk mandi. Sedangkan kemampuan perekonomian orang tuanya rendah untuk sekadar membeli air. Untuk menghemat, anaknya mesti dimandikan.
Bagi Rini, cara itu bukan solusi, melainkan membuka persoalan baru, yaitu rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.
“Karena berulang-ulang menjadi terbiasa. Kalau ada yang membuka bajunya, meraba tubuhnya, dia tidak paham untuk menolak karena selama ini dianggap hal baik dan biasa,” kata Rini.
Baca Juga: Sekolah dan Keluarga Jadi Kunci Pemenuhan Hak Kespro Difabel (2)