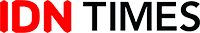Perempuan di Jalan: Minoritas di Tengah Tuntutan Pengesahan RUU PKS
 Seorang demonstran perempuan menunjukkan poster mendukung otonomi perempuan terhadap tubuhnya sendiri pada unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada 26 September 2019. IDN Times/Rosa Folia
Seorang demonstran perempuan menunjukkan poster mendukung otonomi perempuan terhadap tubuhnya sendiri pada unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada 26 September 2019. IDN Times/Rosa Folia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Saya memandangi satu celana jeans pendek yang berada di gantungan. “Ini misi bunuh diri bukan, ya?” batin saya, melebih-lebihkan. Tetapi kegalauan saya pada Rabu malam (25/9) itu tidak mengada-ada.
Beberapa jam sebelum itu, saya sudah memutuskan untuk meliput demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dengan memakai celana pendek, Kamis (26/9), keesokan harinya. Saya juga sudah terlanjur pitching ide ini juga kepada editor dan disetujui.
Alasan saya adalah untuk menguji seberapa inklusif demonstrasi yang salah satu agendanya adalah menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.
“Tetapi apa ini tidak berlebihan?” tanya saya kepada diri sendiri. Ah! Nasi sudah menjadi bubur. Lagi pula, saya sudah kehilangan ide lain.
1. Catcalling sudah pasti terjadi, begitu juga tatapan menyelidik
Saya tiba di kawasan Tugu Pahlawan sekitar pukul 10.30 WIB. Rombongan mahasiswa yang memakai jas almamater tampak melakukan pemanasan. Mereka menyerukan beberapa yel-yel yang dikomandoi oleh seorang orator dari atas mobil bak terbuka.
Polisi-polisi yang mengatur lalu lintas melihat saya dengan pandangan heran. Rasa tidak nyaman mulai muncul. Saya pasang perisai andalan di situasi itu: pura-pura cuek dan percaya diri.
Saya menapaki trotoar untuk mengikuti rombongan tersebut. “Mbak, gak kepanasan? Sini loh ngiyup (berteduh),” kata suara laki-laki dari pinggir jalan. Memang panas. Saya cek siang itu suhu mencapai 33 Derajat Celsius. Suhu khas Surabaya.
Sejumlah mahasiswa laki-laki mulai menyadari kehadiran seorang perempuan "gila" yang datang ke demonstrasi dengan celana pendek. Mereka tampak berbisik-bisik sembari sesekali menengok ke arah saya. Tatapan mereka saya balas dengan sorotan mata yang galak.
Padahal, di dalam hati saya merasa cemas juga. Lautan massa itu hampir semuanya berisi laki-laki. Meski, tentu saja banyak yang tidak peduli pada saya, karena mereka sibuk mengatur barisan atau menyampaikan orasi.
2. Barangkali saya yang keliru dalam membuat keputusan
Proses berpikir saya sebenarnya sederhana. Kalau memang demonstran secara murni berniat menuntut pengesahan RUU PKS, semestinya mereka —baik laki-laki maupun perempuan— akan terbuka terhadap kemungkinan seseorang yang datang dengan memakai pakaian selain celana atau rok panjang.
Soalnya, logika di balik RUU PKS yaitu: bahwa korban adalah korban. Tidak peduli apa pakaiannya. Sambil menyusun rencana, pikiran saya masih berkecamuk dan meragukan keputusan yang telah saya buat sendiri.
Apalagi, ada seorang bapak yang bukan demonstran, duduk di atas jok motor dan secara terus terang memandang ke arah saya, ketika saya berusaha mengambil gambar. Terbesit rasa bersalah dalam diri saya karena terlanjur memakai celana pendek.
Tak berapa lama kemudian, gerombolan pelajar SMP dan STM datang. Salah satunya membawa kardus bertuliskan STM Prapatan. Mereka menyanyikan mars Pak Polisi Tugasmu Mengayomi. Sekelebat, gelombang kecil optimisme menjalar di dalam diri saya. “Ah! Mereka ini yang akan fokus terhadap tuntutan, jadi gak akan peduli pada pakaianku.”
Baca Juga: Mahasiswa Semarang Gelar Aksi Menolak RUU PKS dan KUHP
3. Poster-poster ajaib bertebaran di beberapa titik
Tapi rasa optimis itu seketika menyusut, ketika saya membaca poster yang dibawa seorang anak. Jelas sekali dia masih di bawah umur. "Gak oleh gebleh bojo gebleh gendaan!!!” . Isi poster dalam Bahasa Indonesia berarti kurang lebih, tidak boleh berhubungan seks dengan pasangan sah, akhirnya melakukannya dengan selingkuhan.
“Kamu tahu poster ini maksudnya apa?” tanya saya. Namun, dia hanya tersenyum, lalu bergerak ke pinggir. Seorang laki-laki yang lebih dewasa - yang saya duga adalah koordinator demo - lalu memintanya membuang poster tersebut.
“Gak oleh ngene iki (tidak boleh begini ini),” ucap dia. Poster itu sepertinya merujuk kepada Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan pelaku perkosaan terhadap pasangan sah, bisa terkena hukuman pidana kurungan paling lama 12 tahun penjara.
Perkosaan sendiri diartikan memaksa seseorang melakukan hubungan badan tanpa persetujuan, dan ini bisa terjadi dalam rumah tangga. Poster lainnya tidak kalah ajaib. “Lek kentu bojo dewe onok hukumane lha ape mbok kongkon ngentu bojoe tonggo ta” atau yang kurang lebih berarti, jika melakukan seks dengan pasangan sah sendiri ada hukumannya, apakah kamu menyuruh berhubungan badan dengan pasangan tetangga.
Lagi-lagi poster itu dibawa anak usia sekolah. Tentu ini mengherankan. Beberapa pelajar yang saya temui enggan menjelaskan dari mana poster itu berasal atau mengapa isinya seperti itu.
Poster bertema seks sepertinya sangat digemari oleh beberapa anak muda. Seorang mahasiswa lain terlihat membentangkan poster bertuliskan bahwa aktivitas seksnya “mulai terancam”.
4. Tiga lawan banyak dan akhirnya kami memilih bersikap tenang
Saya memutuskan masuk ke dalam barisan, ketika massa mulai bergerak ke arah gedung DPRD. Saya sengaja menempel ke dua demonstran perempuan yang memakai jilbab. Namanya Vina dan Wulan. Keduanya sudah saya perhatikan selama beberapa saat.
Segerombolan pelajar laki-laki langsung mendekati mereka dan mengajak berkenalan. Di dalam barisan, tuntutan penolakan, revisi, maupun pengesahan RUU pun sejenak terlupakan.
Laki-laki di depan, belakang dan samping kiri-kanan kami kini fokus bertanya nama dan melontarkan kalimat-kalimat yang membuat saya mengernyitkan dahi. "Mbak, aku lek oleh sampean, aku mandeg dulinan layangan (Mbak, kalau aku mendapatkan kamu, aku berhenti bermain layang-layang),” celetuk salah satunya.
Saya bertanya kepada Wulan dan Vina apakah mereka tidak takut datang ke demonstrasi yang sangat didominasi laki-laki tersebut. “Biasa saja sih, mbak. Soalnya saya tahu mereka ini cuma beraninya kayak gini,” kata Vina, yang disambut anggukan kepala Wulan, tanda setuju.
Saat saya minta keduanya berfoto, para pelajar itu mendadak ikut berpose. Selama beberapa puluh meter ke depan, ada kesepakatan tidak langsung di antara kami untuk sebaiknya bersikap tenang.
5. Ada remaja laki-laki yang khawatir, ada juga ibu-ibu yang mencibir
Editor’s picks
Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya saya meliput aksi dengan menggunakan celana pendek. Saya pernah mengenakannya ketika meliput Women’s March pada April 2019 lalu di Jakarta.
Kala itu, tidak ada kejadian yang membuat saya tidak nyaman. Ketika berangkat pun tidak ada rasa khawatir yang menggerayangi pikiran. Tentu ada satu atau dua orang yang tidak setuju dengan apa yang saya pakai, karena menilai saya mencoreng nama baik media tempat saya bekerja.
Selebihnya, memilih diam atau tidak menganggap ada persoalan pada pakaian saya. Sejauh ini tidak pernah ada teguran apa pun kepada saya dari atasan, jadi saya anggap baik-baik saja.
Yang merasa tidak baik-baik saja adalah empat ibu-ibu berniqab. Salah satu kesialan yang disebabkan pemerintah pada demo kemarin adalah diberlakukannya throttling atau pelambatan sinyal di area sekitar demonstrasi.
Akibatnya, saya harus menyingkir ke trotoar seberang gedung DPRD. Persisnya di depan Masjid Kemayoran. Ibu-ibu tersebut tak berusaha menutupi ketidaksukaan mereka terhadap pakaian saya.
Sambil memandangi dari atas ke bawah, salah satunya menyindir,”Ben isis be’e (biar sejuk mungkin)”. Akan tetapi karena prioritas saya adalah mengirim berita, tentu mereka tidak terlalu saya pedulikan. Setelah berita terkirim, saya teringat kepada dua remaja 14 tahun, Barok dan Arya.
Beberapa saat sebelumnya, saya melihat keduanya seperti terasing dari massa, lalu saya ajak bicara. Mereka mengaku ikut demonstrasi karena kesadaran sendiri. “Memang apa yang kalian anggap bermasalah?” tanya saya secara spontan.
“Ya, misalnya kayak perempuan pulang malam lalu didenda. Kan kasihan yang kerja,” kata Barok. Di balik masker, saya tersenyum mendengar jawaban itu. Saya pun meminta salah satunya memberikan pendapat soal pakaian saya.
Barok kembali merespons. Ia merasa bisa saja ada yang mencolek saya karena berpakaian begitu. “Gimana ya… Mungkin khawatir aja,” tambahnya.
Tidak ada yang mencolek saya. Beberapa anggota massa memandangi, mengeluarkan komentar-komentar tidak layak, berusaha menggoda atau bisa juga kita sebut catcalling. Namun, sedih rasanya saat yang melakukannya adalah aparat dan wartawan. Salah seorang teman yang bersama saya dalam dua jam terakhir jadi saksinya.
“Cantik kok gak di kantor aja, malah jadi wartawan? Nanti hitam lho,” kata seorang bapak yang juga berprofesi sebagai jurnalis. Sementara beberapa aparat berbisik-bisik dengan sesama rekannya, mencoba menahan tawa sambil melihat ke arah saya.
6. Masalah perempuan belum mendapat porsi maksimal
Saya sendiri kesulitan menemukan harmonisasi antara sikap dan tuntutan massa yang menjadi inti dari demonstrasi itu. Barangkali karena banyaknya RUU yang dipersoalkan, sehingga tak sedikit pengunjuk rasa yang bingung harus fokus ke mana. Mungkin juga karena mahasiswa dan pelajar belum bisa mengorganisir diri secara solid.
Misalnya, ketika orasi berlangsung di titik tengah, ada kelompok mahasiswa dari sebuah kampus yang memilih berdiri agak jauh dan menandai area mereka dengan tali rafia. Saya sempat dilarang melintas oleh salah satu koordinatornya, meski saya katakan bahwa saya sedang meliput.
Namun, yang pasti adalah RUU PKS tidak mendapatkan porsi maksimal. Dari seluruh orasi yang sempat saya dengar - yang ditandingi dengan kidungan Asmaul Husna dari Masjid Kemayoran sepanjang demonstrasi- hanya satu orator yang dengan tegas menuntut pengesahan RUU PKS. Dia adalah Palupi, Ketua Women’s Crisis Center dari Jombang.
“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak berbicara tentang pelegalan perzinaan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak bicara tentang LGBT, tapi RUU ini bicara tentang keadilan, tentang hak korban-korban kekerasan seksual,” kata Palupi dari atas mobil komando.
Dalam wawancara sebelum orasi, Palupi menegaskan, organisasinya hadir siang itu karena data kekerasan seksual sudah mengkhawatirkan. Menurut Komnas Perempuan, pada 2018 lalu ada 406.178 kasus atau meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya.
Ini paling tinggi terjadi di ranah privat, salah satunya yaitu perkosaan dalam rumah tangga. Di ranah publik, ada 2.448 kasus dan mayoritas terjadi di jalan.
Survei oleh change.org Indonesia, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Hollaback! Jakarta dan Perkumpulan Feminis Indonesia pada 2019 menunjukkan 60 persen dari 62.000 responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk verbal.
Sedangkan sebanyak 51 persen yang mengalaminya memakai rok atau atasan panjang. Ini menangkis anggapan bahwa pelecehan seksual di ruang publik hanya menimpa individu berpakaian terbuka.
“Tapi apa faktanya? Regulasi yang dibutuhkan korban belum juga disahkan,” tambahnya. “Beberapa waktu lalu DPR mengatakan pengesahan RUU PKS menunggu pengesahan RUU KUHP. Faktanya RUU KUHP juga bermasalah,” tegasnya. “Ini menunjukkan DPR tidak serius dalam menangani korban kekerasan.”
7. Demonstrasi masih dikuasai laki-laki, padahal kita butuh inklusi
Partisipasi politik, termasuk melalui demonstrasi, masih didominasi oleh laki-laki. Ini bukan fakta mengejutkan, sekalipun apa yang jadi salah satu tuntutan adalah masalah yang paling banyak dialami perempuan.
Dalam RUU PKS, relasi kuasa diakui sebagai fakta yang bisa menyebabkan kekerasan seksual. Tak terkecuali dalam bentuk kedipan atau komentar merendahkan dan bernada sensual.
Ini terbukti terjadi sepanjang demo yang tentu saja kontra-produktif dengan tujuan semestinya. Vyo Trivia, perempuan yang mengikuti demo bersama satu temannya, mengeluhkan hal serupa dengan saya. Menurutnya, ”poster-posternya nyeleneh” dan “malah kelihatan ngelecehin perempuan”.
Ia juga mengaku digoda oleh sekelompok mahasiswa ketika berada dalam barisan. Medis perempuan, kata dia, turut menjadi target. Sementara itu, meski baru demo pertama yang diikutinya, ia belum putus asa. “Kalau ada demo lagi pasti saya ikut, tapi lihat dulu isinya apa,” katanya, sambil menambahkan harapan agar apa yang terjadi kemarin tidak terulang lagi.
Peristiwa-peristiwa seperti itu yang selama ini membuat perempuan enggan mengikuti unjuk rasa. Perempuan seperti harus serius memikirkan pakaian serta posisi secara saksama - sesuatu yang tidak perlu dipertimbangkan masak-masak oleh laki-laki.
Ketika memberanikan diri berdemo, tak sedikit yang malah dipotret karena paras mereka rupawan. Hal yang justru mendorong laki-laki untuk menggoda. Di media sosial sendiri muncul imbauan agar peserta unjuk rasa di Jakarta pada Senin esok (30/9) tidak melakukan catcalling, meneriakkan komentar seksis serta melecehkan.
Artinya, apa yang terjadi di Surabaya pada Kamis kemarin bukan fenomena terselubung, melainkan sudah jadi sesuatu yang biasa.
Tapi, kalau mau melangkah maju, mari hentikan ini sebagai kebiasaan. Sudah saatnya perempuan-perempuan mengisi mimbar-mimbar demokrasi di jalanan tanpa takut nanti menjadi korban pelecehan.
Baca Juga: Massa Aksi Mujahid 212 Tidak Hanya Tolak RUU KUHP, Tapi Juga RUU PKS